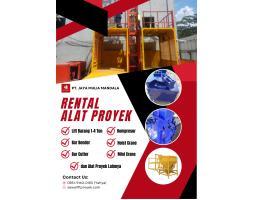INDEF: Celah Aturan Cukai Rokok Bikin Penerimaan Negara Tak Optimal
INDEF menilai ada sejumlah celah dari sejumlah aturan tersebut yang membuat penerimaan negara dan pengendalian konsumsi rokok tidak optimal.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, ada tiga temuan terkait kebijakan cukai rokok.
Menurut Tauhid, terdapat sejumlah celah dari sejumlah aturan tersebut yang membuat penerimaan negara dan pengendalian konsumsi rokok tidak optimal.
Aturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2018 mengenai Perubahan PMK 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang merupakan peraturan turunannya.
"Pertama, struktur cukai saat ini masih belum mengakomodir persaingan yang berkeadilan dan cenderung memiliki celah yang mampu dimanfaatkan," katanya dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca: Tanggapan Istana Soal Artikel Dahlan Iskan yang Sebut Prabowo Miliki Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru
PMK 146/2017 yang direvisi menjadi PMK 156/2018 membuat golongan tarif cukai rokok berdasarkan jenisnya yaitu sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT).
Golongan tarif itu disusun berdasarkan produksi untuk membedakan perusahaan besar dan kecil.
Namun, INDEF menemukan bahwa perusahaan rokok besar masih bersaing dengan perusahaan kecil.
“Golongan tarif berdasarkan jumlah produksi cukup berpengaruh terhadap tingkat persaingan berkeadilan (level playing field),” jelas Tauhid.
Temuan kedua INDEF adalah dari tujuh perusahaan rokok multinasional terdapat indikasi pelaku industri besar yang memproduksi dalam jumlah banyak membayar tarif cukai rokok pada golongan rendah.
“Jika perusahaan rokok yang membayar tarif cukai pada golongan 2B (rendah) memproduksi 1 miliar batang dengan harga jual eceran (HJE) minimum Rp 715 per batang, maka pendapatan kotornya adalah Rp 715 miliar. Apakah ini termasuk perusahaan kecil?,” kata Tauhid.
Meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah mengatur bahwa perusahaan dengan penjualan di atas Rp 50 miliar per tahun termasuk kategori usaha besar, namun dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunannya tidak mengkategorisasikan skala usaha industri rokok tersebut melainkan hanya mengacu pada jumlah produksi rokok.
Ketiga, keberadaan 'diskon rokok' yang menyalahi konsep cukai sebagai instrumen pengendalian dan berpotensi membuka peluang persaingan yang tidak berkeadilan.
Diskon rokok terjadi salah satunya akibat level playing field yang tidak setara.
Ketentuan Diskon Rokok diatur melalui Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 37/2017.
Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85% dari harga jual eceran (HJE) yang tercantum dalam pita cukai.
Produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari HJE asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.
Selain bertentangan dengan tujuan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, keberadaan diskon rokok juga turut membuat penerimaan negara tidak optimal.
Dari 1327 merek rokok yang diteliti pada April 2019, sebanyak 46,8 persen diskon terjadi pada sigaret kretek mesin yang membayar tarif cukai golongan yang rendah.
“Diskon banyak dilakukan oleh pelaku dengan tingkat persaingan besar,” kata Tauhid.
Adanya potensi optimalisasi penerimaan negara dari pajak penghasilan rokok hingga Rp 1,73 triliun jika kebijakan ini dikaji ulang pada tahun ini.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan