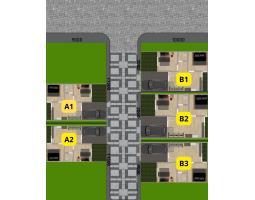Dugaan Rekayasa Kasus JIS Kembali Mencuat di Sidang Guru
Dugaan adanya unsur rekayasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School (JIS) kembali mencuat.
Editor: Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan adanya unsur rekayasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School (JIS) kembali mencuat.
Kali ini fakta tersebut terungkap dalam sidang yang melibatkan dua guru JIS yaitu Neil Bantleman dan Ferdinant Tjong.
Dalam sidang tertutup yang berlangsung hingga Selasa malam terungkap, sejumlah saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diduga masih terafiliasi dengan ibu korban.
Selain itu, para ahli yang terdiri dari psikolog tersebut tidak memiliki kompetensi serta tidak didukung oleh pengetahuan serta pengalaman yang memadai.
Demikian dikemukakan, Henock Siahaan, salah satu pengacara dua guru JIS, Rabu (21/1/2015).
Dijelaskan dua orang psikolog yaitu Connie Kristianto dan Nella Safitri merupakan psikolog dari pelapor kasus ini yaitu TPW dan DAR.
Ibu dari korban MAK dan CAP meminta dua psikolog itu untuk memberikan konseling kepada anak mereka sejak kasus ini mencuat ke publik.
Sementara itu, dua ahli lainnya yaitu Nurul Adhiningtyas dan Setyani Ambarwati merupakan psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di DKI Jakarta.
Lembaga ini merupakan mitra Polda Metro Jaya, pihak yang menjadi penyidik kasus JIS.
“Pemilihan dan penunjukan ahli yang dihadirkan dalam persidangan kemarin sangat tidak independen dan meragukan. Seharusnya ahli yang dihadirkan tidak memiliki afilisasi dengan pihak-pihak yang terlibat, apalagi sampai dibayar oleh ibu yang diduga anaknya menjadi korban kasus ini,” kata Hennock.
Adanya hubungan antara saksi ahli dengan TPW terlihat dari semua keterangannya tidak independen dan bias. Selain itu, keahlian dari para saksi juga meragukan.
Hennock mencontohkan, dalam keterangannya Setyani mengatakan bahwa “Anak tidak mungkin berbohong”.
Tapi pada keterangannya yang lain ia menyatakan bahwa “anak kalau dipaksakan bisa berbicara apa saja”.
Dalam ilmu psikologi sendiri teori “anak yang tidak mungkin berbohong” merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Catherine Fuller tahun 1984.
Teori ini ada sebelum peristiwa tuduhan kekerasan seksual palsu yang terjadi di TK McMartin di Amerika Serikat. Namun, setelah kasus di TK McMartin tersebut teori anak tidak mungkin berbohong sudah ditinggalkan oleh dunia psikologi.
Sebagai ahli, Setyani juga hanya mengumpulkan informasi sepihak yaitu dari ibu korban dan polisi. Dalam keterangannya psikolog yang ditunjuk Polda Metro mendampingi MAK sejak bulan Maret 2014 ini mengungkapkan, dia tidak mengumpulkan informasi dari pihak sekolah karena tidak mendapatkan ijin.
Padahal Setyani juga mengakui bahwa dirinya belum pernah mengirimkan surat resmi kepada JIS untuk datang dan melakukan pengumpulan informasi terkait kasus ini.
“Semua keterangan yang disampaikan ahli sangat bias dan tidak relevan untuk didengar. Sangat berbahaya menggunakan keterangan ahli yang sudah memiliki afiliasi dengan salah satu pihak,” tandas Hennock.
Tak Pernah Menyebut Neil dan Ferdi
Ahli lainnya yaitu Connie Kristanto, mengaku diminta oleh orang tua MAK untuk memberikan therapi terhadap anaknya, MAK, sebanyak 30 kali sesi.
Selama 30 sesi bersama MAK, Connie mengakui bahwa si anak tidak pernah menyebut nama Neil dan Ferdi.
Lebih penting lagi, lanjut Hennock, Connie mengaku hanya memiliki spesialisasi di psikologi klinis. Keahlian itu tujuannya hanya mengobati dan memberikan terapi. Connie tidak punya keahlian psikologi forensik.
Oleh karena itu, dia tidak pernah menggali apa latar belakang kejadian yang diduga menimpa MAK dan siapa pelakunya.
Selama berulang kali sesi pemeriksaan anak dengan Connie, anak tidak pernah ditanya mengenai kedua hal tersebut. Sebagai ahli Connie juga tidak memiliki pengetahuan mengenai false memory.
False memory atau memori palsu adalah sebuah ingatan yang tercipta dari penciptaan kenangan palsu, persepsi palsu atau keyakinan palsu tentang diri atau lingkungan. Penciptaan ingatan ini menimbulkan kebingungan sehingga seseorang tidak mampu lagi membedakan apakah ingatan tersebut benar atau salah, benar-benar terjadi atau tidak pernah terjadi. "Seharusnya saksi ahli yang kompeten adalah psikiatri forensik.
Dengan demikian dapat memeriksa kejiwaan anak untuk mengetahui penyebab trauma psikologis dan saat memberikan keterangan dapat dinyatakan masuk akal. Dan yang lebih penting, ahli harus independen,” ujar Hennock.
Dalam UU kesehatan No. 36 Tahun 2011 pasal 150, ayat 1 tentang pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Sedangkan ayat 2 tentang penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.
"Mengingat saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menangani kasus ini, tidak independen dan ahli tidak mengikuti perkembangan metode penanganan psikologis anak, kami berharap majelis hakim mempertimbangkan untuk mengenyampingkan kesaksian ahli hari ini,” kata Hennockmengakhiri percakapan.
Sebelumnya kepada media, Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) menilai penunjukan saksi ahli yang tidak memiliki kompetensi berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran saksi ahli memiliki peran penting dalam pengungkapan kebenaran dan mewujudkan keadilan.
"Saksi ahli itu harus memberikan kejelasan untuk suatu kasus. Jadi harus dilihat jenjang akademisnya, (apakah dia) memiliki pengalaman menangani kasus serupa apa belum. Keterangan saksi ahli menjadi barang bukti. Kalau tidak kompeten maka akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum," kata Ketua Umum Peradi,Otto Hasibuan, Senin (19/1/2015).
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan