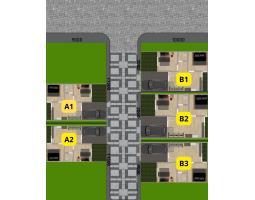Nasihat Nietzsche untuk Mourinho dan Guardiola
Peraduan mereka tetap menyisakan cerita tersendiri yang layak untuk dikisahkan sebagai ornamen Premier League, tempat mereka berdua kekinian berpentas
Persaingan Jose Mourinho dengan Josep “Pep” Guardiola, sebenarnya bukan hikayat baru. Namun, peraduan mereka tetap menyisakan cerita tersendiri yang layak untuk dikisahkan sebagai ornamen Premier League, tempat mereka berdua kekinian berpentas.
MOURINHO dan Guardiola sepertinya ditakdirkan untuk selalu berdekatan—tapi pada saat yang bersamaan pula—sekaligus seakan menjadi dua kutub yang berjauhan plus bertolak belakang di dunia sepak bola.
Guardiola, biasanya diidentifikasi sebagai pelatih “idealis”, rendah hati, dan dipenuhi ide-ide nan filosofis untuk tetap memainkan gaya sepak bola indahnya yang sudah tersohor: tiki-taka. Entah itu di Barcelona, Bayern Muenchen, atau Manchester City, permainan indah selalu menjadi sajian utama.
Watak Guardiola yang keras kepala untuk tetap menerapkan tiki-taka, sebenarnya tidak moncer-moncer amat pada tataran praktis. Selain di Barcelona, idenya itu bisa dikatakan tidak cukup berhasil di Muenchen—jika paramaternya adalah melampaui prestasi pendahulunya, Jupp Heynckes.
Namun, melalui hasil positif yang diraih Manchester City pada laga-laga awal EPL serta play-off Liga Champions, banyak pihak berharap tiki-taka bakal cocok diterapkan di tanah Inggris.
Sementara persona Mourinho dinilai sebaliknya. Arogan, sombong, pragmatis dalam taktik, serta tak peduli terhadap keindahan. Meraih kemenangan, seakan menjadi satu-satunya ide yang ada di kepala sosok yang menyebut dirinya sendiri sebagai “The Special One.”
Tapi, sikap degilnya itu membuat Porto mampu menjadi jawara Liga Champions, mengangkat Chelsea sebagai kampiun Liga Inggris, Internazionale Milan meraih treble winner, dan Real Madrid bisa “menginterupsi” dominasi Barcelona.
Sadar ataupun tidak, penilaian umum yang menempatkan Mourinho dan Guardiola pada arena oposisi biner seperti itu sebenarnya tidak salah. Sebab, Justru penempatan semacam itu membuat sepak bola yang sudah menjadi komoditas di dunia kapitalisme maju Eropa, masih memiliki nilai keindahan dan bernilai estetik.
Tak percaya?
Apollonian dan Dionysian
Oposisi biner “Mou vs Pep” mengenai keindahan sepak bola itu tampaknya menjadi pembenaran bagi alegori filsuf Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche, dua abad silam.
Terkait seni dan keindahan (estetika), dalam karya pertamanya berjudul “The Birth of Tragedy from the Spirit of Music” (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik; Lahirnya Tragedi dari Jiwa Musik), Nietzsche mengatakan kedua hal tersebut sudah tak lagi ada karena dirusak oleh negara. Alhasil, manusia tak lagi bisa merasakan kebahagiaan.
Fanatisme dan kedisiplinan kaku yang selalu diajarkan negara, ternyata bukannya melestasikan keindahan seni, tapi justru menghancurkannya.
Bagi Nietzsche yang dikenal sebagai “Si Pembunuh Tuhan” ini, terdapat dua semangat yang seharusnya tetap dihidupkan agar segala seni dan keindahan tetap ada dan mampu membahagiakan manusia. Kedua semangat itu ialah Apollonian dan Dyonisian, yang diadopsi dari dua nama dewa Yunani arkais.
Apollonian merupakan semangat kejeniusan, mengedepankan keharmonisan serta keindahan, dan segala kemampuan untuk menghadirkan seni bermutu tinggi sehingga mampu menutup kenyataan-kenyataan penuh kemalangan.
Sedangkan Dionysian, adalah simbolisasi semangat penuh “kegilaan”, ekstase, keinginan untuk menghancurkan semua norma kehidupan yang sudah mapan, teratur/harmonis, mekanistik, dan rasional. Semangat yang tak mau terkekang oleh kemapanan.
Dionysian cenderung berada di kutub negatif, tapi sangat dialektik. Jika tak ada semangat Dionysian, tak bakal ada seni tinggi. Sebab, nilai estetik dalam kebudayaan selalu lahir dari rahim konflik, perseteruan.
Jika hanya ada semangat Apollonian, maka keindahan akan menjadi stagnan, tak berkembang, lalu menjadi totem atau mati.
Meski bertolak belakang, kedua simbolisasi semangat ini tak bisa dipisahkan, bahkan saling memengaruhi. Alhasil, pertautan kedua oposisi biner itu justru menciptakan hal-hal baru yang secara superfisial menyatu: keindahan seni.
Negara yang disebut Nietszche sebagai pembunuh seni dan keindahan itu, tampaknya bisa diwakilkan sebagai kekuatan modal berbagai taipan dunia sepak bola.
Tak peduli laga itu berjalan seperti apa, yang penting tiket, pernak-pernik, bursa taruhan, dll, menguntungkan dan menambah pundi-pundi uang para pemodal.
Tapi, itu bukan berarti sepak bola kekinian tak lagi memiliki nilai estetis yang mampu membuat penggemarnya bahagia.
Setidaknya, ada Guardiola yang mewakili semangat Apollonian dan Mourinho “si Dionysian” yang lewat perseteruannya, mampu kembali menghadirkan keindahan tersendiri dalam sepak bola.
Kemungkinan, banyak pihak yang merasakan ada “sesuatu yang hilang” di La Liga Spanyol, ketika Mou dan Pep memilih hengkang dari kompetisi itu.
Meski pesona Barcelona terus bersinar, dan kemegahan Real Madrid semakin kuat, tetap saja tak semenarik saat Pep dan Mou saling lempar sindiran ketika konferensi pers, serta adu taktik di lapangan.
Kekinian, jika Mourinho dan Guardiola mau mendengarkan "nasihat" dari Nietzsche itu, kita boleh lah berharap bisa merasakan ekstase saat menyaksikan Manchester United vs Manchester City sembari “deg-deg-ser”. (Reza Gunadha)
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan