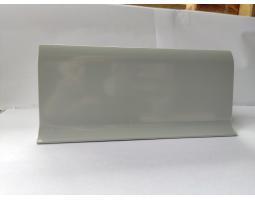Kondisi Keluarga Melarat Ini Kontras Dengan Citra Bali sebagai 'Pulau Surga' Wisata
Di balik citra Bali sebagai 'Pulau Surga' wisata, ternyata masih belum bebas dari wajah-wajah kemiskinan. Seperti di pedalaman Bangli ini.
Editor: Agung Budi Santoso

TRIBUNNEWS.COM, BANGLI- Kehidupan sepuluh keluarga di Gege (hutan) Bukit Bawa, Kecamatan Kintamani, Bangli, sangatlah memprihatinkan, dan sungguh berbeda dengan keelokan citra Bali sebagai salah-satu pusat wisata dunia. Di tengah segala keterbatasan, mereka mencoba terus bertahan hidup.
Tribun Bali sempat langsung menyusuri lokasi yang memerlukan waktu tempuh sekitar 5 jam perjalanan dari Denpasar itu, Senin (17/11). Jalur yang dapat diakses menggunakan sepeda motor hanya sampai di Desa Blandingan, dua jam berikutnya harus berjalan kaki, menaiki bukit dan menapaki jalan terjal menurun.
Medannya bisa dikata tidak mudah, bahkan bagi para pendaki sekalipun. Hampir sebagian besar rutenya menanjak, hanya sesekali landai. Beberapa area langsung bersebelahan dengan jurang.
Jalan setapak yang cukup sempit, ditambah tanah berdebu pada lahan gersang dan ketidaktersediaan air, membuat perjalanan semakin berat. Sekali seseorang menjejakkan langkah, debu akan langsung berhampur, bahkan sampai setinggi tubuh.
“Saya sering mendaki gunung dan keliling Bali membantu anak-anak, tapi ini daerah paling berat yang pernah saya telusuri. Sebenarnya sempat ada beberapa media, termasuk TV nasional yang ingin ke sini, tapi belum ada yang berhasil. Mereka menyerah,” tutur Joni Wardana Putra (22), pemuda asal Desa Songan, Bangli, yang juga aktif di Komunitas Anak Alam, Bali.
Para keluarga yang memutuskan tinggal di tengah hutan itu sesungguhnya berasal dari Banjar Buluh, Desa Songan B, Kintamani, Bangli. Mereka memilih pindah ke hutan karena di daerah asalnya tidak banyak yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup.
Keluarga yang pertama kali menempati Gege Bukit Bawa datang sekitar tahun 1994. Pada saat itu sedang terjadi transmigrasi besar-besaran ke luar Bali, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Ketakutan untuk ditransmigrasikan oleh pemerintah ke luar Bali menjadi alasan lain yang membuat mereka memilih tinggal di dalam hutan.
“Sejak hampir 20 tahun lamanya, tidak pernah ada yang tahu keberadaan mereka. Baru tahun ini ada yang datang," tutur Joni.
Karenanya, masyarakat setempat merasa begitu bahagia apabila ada orang yang berkunjung.
Joni lanjut menceritakan,“kami mendapat informasi ini karena tidak sengaja bertanya kepada seorang anak yang sekolah di SD Blandingan. Katanya, dia tinggal jauh. Saya bingung, maksudnya jauh dimana. Kemudian saya dan kawan-kawan mengikuti dia, dan barulah kami tahu ternyata di sini mereka tinggal.” Joni bersama dua kawannya, Jro Komang Karma dan Pande Putu Setiawan menemani penelusuran Tribun Bali.
Saat tiba di rumah pertama, tampak seorang anak perempuan bernama Murni berdiri. Pakaiannya lusuh, ia sangat malu dan tidak mau banyak bicara. Di dalam sebuah gubuk kecil yang sudah tua di belakangnya, ia hanya tinggal bersama neneknya.
Di pertengahan jalan menuju rumah berikutnya, rombongan sempat bertemu nenek Murni. Ia sudah sangat renta. Meskipun begitu, ia tetap naik turun gunung mencari rumput atau bahan makanan.
Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya terbilang cukup jauh, terpaut sekitar 10 sampai 20 menit perjalanan. Hampir semua berupa gubuk berukuran sekitar 3 x 4 m, hanya dibangun dari batang pohon, ulatan bambu sebagai dinding dan alang-alang untuk atapnya.
Bahkan ada warga yang rumahnya tidak berdinding, sehingga mereka kerap kedinginan, terutama pada musim hujan.
Satu ruangan itu langsung digunakan sebagai tempat tidur, memasak dengan kayu bakar, dan menyimpan barang. Mereka tidur di atas satu dipan sederhana berukuran sekitar 1 x 1,5 m, tanpa alas maupun bantal.
Saat malam hari Tribun Bali tiba di kediaman Wayan Daftar (40) yang merupakan penghuni pertama di Gege, kedua anaknya tengah tidur di tanah, hanya beralaskan terpal. Tampak spanduk kampanye seorang caleg yang sudah robek di beberapa sisinya dipakai untuk dinding penutup.
Pada rumah lainnya, spanduk kampanye pemilihan gubernur pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta, juga Puspayoga dan Sukrawan, dipakai menambal bagian rumah yang berlubang. Gelas plastik bekas minuman, mereka gunakan berulang kali layaknya gelas kaca atau keramik.
“Pakaian mereka sangat sedikit, satu baju bisa dipakai berbulan-bulan. Saya masih tidak percaya ada yang hidup kayak begini, di Bali lo,” kata Joni seraya mengajak Tribun Bali masuk ke dalam rumah seorang warga.
Selain itu, karena tidak ada listrik, sehalri-harinya mereka hanya diterangi sinar matahari dan cahaya bulan.
Wayan Daftar beserta masyarakat setempat mengaku meskipun hidup sangat sederhana dan dalam segala keterbatasan, tapi mereka selalu mencoba mensyukurinya.
Walaupun harus dua jam berjalan untuk anak-anaknya bersekolah dan dua jam hanya untuk membeli beberapa jeriken air di Desa Tembok, Buleleng, mereka belum ada keinginan pindah.
Sebelumnya mereka sempat melapor ke pemerintah Kabupaten Bangli untuk mendapat izin tinggal di tanah milik pemerintah itu. Mereka pun diperkenankan menempatinya dalam rentang waktu 70 tahun, dan diminta untuk melakukan tanam dengan pola tumpang sari. (Ni Ketut Sudiani)
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan