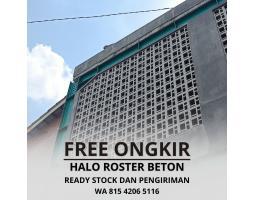Jokowi dan Gunung Jamurdipa
Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia "hanyalah" Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Editor: Hasanudin Aco
Adalah tragis, rakyat yang mayoritas itu menjadi minoritas yang minder. Sebagai presiden, Jokowi bertanggung jawab mengembalikan rakyat sebagai mayoritas dan menghilangkan minderheid-kompleksnya. Untuk itu, Jokowi perlu meraih kembali momen kairos dan percaya bahwa dalam kairos terhimpun kekuatan politik rakyat yang punya satu-satunya kehendak, yakni perubahan. Jika mau melakukan ini, Jokowi berpeluang besar merebut kembali kepercayaan rakyat, yang kini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap para wakilnya di DPR. Revolusi mental Jokowi mandul dan berhenti di tempat karena tak mengorientasikan diri pada kekuatan rakyat. Di sini pun Jokowi perlu kembali pada kairos, yang telah membawanya ke kursi pimpinan tertinggi di negeri ini. Kairos itu adalah kekuatan sejarah, yang dalam arti tertentu "liar" dan bernalurikan "petualangan". Jokowi perlu menyuntikkan daya dobrak kairos itu ke dalam revolusi mentalnya, supaya revolusi mentalnya memperoleh "darah segar" untuk menabrak dan mengubah kemapanan demi tercapainya cita-cita tanah air Nusantara baru yang adil, damai, dan tenteram seperti diinginkan rakyat.
Ziarah gunung
Jadi, jika mau, dengan bantuan kairos itu, Jokowi berpeluang bisa menjadi paku Gunung Jamurdipa bagi tanah air Nusantara yang sedang gonjang-ganjing ini. Gunung Jamurdipa telah menjadikan gunung-gunung di Nusa Jawa. Bagi orang Jawa, ini semua simbol laku yang punya makna. Gunung itu dhuwur, tinggi. Sementara rakyat biasanya sering disebut sebagai wong gunung. Gunung lalu jadi simbol kekuatan rakyat yang keluhuran dan tingginya bahkan melebihi keluhuran raja atau priayi. Jokowi bukanlah ketua partai, keturunan raja, atau priayi. Ia rakyat biasa, wong gunung. Tetapi justru dalam dirinya tersimpan martabat luhur rakyat. Karena itu, ia jangan minder terhadap kekuasaan mana pun.
Untuk memperkuat keyakinannya sebagai wong gunung, Jokowi perlu menjalani kembali laku gunung. Dari Gunung Prau di barat, ia harus naik perahu, ke timur, ke Gunung Slamet. Di sana ia akan dicerahkan, bahwa rakyat sesungguhnya hanya punya cita-cita amat sederhana, yakni slamet. Dengan menjalani laku Gunung Slamet, rakyat akan merengkuhnya untuk bersama-sama meraih slamet, hingga akan selamat pula pemerintahannya. Dari Gunung Slamet ia mesti melanjutkan laku Gunung Kendil. Di sinilah ia dapat mempertajam intuisinya, bahwa rakyat itu kendil atau periuk bagi pemerintahannya. Tak mungkin pemerintahannya berjalan tanpa periuk rakyat itu. Namun, sebagai imbalannya, ia tak boleh membiarkan rakyat sengsara dan mati karena periuknya mati asap. Maka, dengan hikmah Gunung Kendil, Jokowi bisa menggali kembali program-programnya yang pro rakyat, agar periuk rakyat cepat berasap.
Dari Gunung Kendil, Jokowi harus melanjutkan laku Gunung Petarangan. Petarangan adalah tempat induk ayam bertelur dan mengeraminya. Maka laku Gunung Petarangan mengingatkan, jangan Jokowi lupa akan asal-usulnya. Ia bukan jenderal, ketua partai, atau anak raja. Tetapi begitu jadi presiden, Jokowi mungkin lupa bahwa ia adalah wong cilik, atau rakyat biasa. Maklum, kekuasaan mudah membuat lupa. Karena itu Jokowi tidak perlu menaikkan martabatnya karena martabat rakyat itu adalah terluhur. Juga ia tak perlu mengenakan predikat apa-apa lagi. Ia tak perlu, misalnya, memakai seragam dan baret tentara, yang di zaman Orde Baru telah demikian menakut-nakuti rakyat. Ibaratnya, ia cukup memakai kemeja rakyatnya, "kemeja putih", di mana terpantul cahaya ketulusan, kejujuran, kesederhanaan, martabat luhur rakyatnya.
Dengan laku Gunung Petarangan ini Jokowi boleh teringat kembali saat ia mengumumkan deklarasi pencapresannya. Deklarasi itu dilakukannya di Rumah Si Pitung, Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara. Si Pitung adalah pendekar Betawi yang mati-matian membela rakyat melawan kompeni. Jokowi kiranya ingin terkena aura roh perlawanan rakyat itu. Maka, setelah jadi presiden, janganlah ia hanya berani menghukum mati, tapi juga "berani mati" seperti Si Pitung yang berani mati dihukum gantung oleh kompeni. Sekarang banyak sekali kompeni di sekitar Jokowi: kompeni-kompeni bisnis, kompeni-kompeni politik, kompeni-kompeni partai, dan kompeni-kompeni kepentingan. "Perlawanan", kata Jokowi saat di Rumah Si Pitung itu. Sekarang Jokowi sungguh ditantang, untuk bersama rakyat melawan kompeni-kompeni di sekitarnya itu. Maka, demi rakyat dan karena roh perlawanan Si Pitung, ia juga harus berani melawan jika ia dijadikan boneka atau petugas partai oleh kekuasaan oligarkis partai pendukungnya sekalipun.
Dari Gunung Petarangan, Jokowi harus meneruskan laku Gunung Merapi. Sampai sekarang di sana masih menyala api dari perapian Hempu Ramadi. Di perapian itu Jokowi boleh menghangatkan dan membakar kembali semangat gunungnya, semangat kerakyatannya, yang akhir-akhir ini sempat padam atau dipadamkan. Jokowi harus terus menyalakan api perjuangan rakyatnya. Untuk itulah akhirnya ia perlu kembali ke asalnya, ke Gunung Lawu. Jokowi adalah anak Solo yang terletak di kaki Gunung Lawu. Maka laku Gunung Lawu akan mengajak dia ngawu-awu atau bertanya tentang asal-usulnya. Asal-usulnya rakyat kecil biasa. Di Solo ia thukul, tumbuh sebagai wong Solo seperti Wiji Thukul. Maka, seperti Wiji Thukul yang tumbuh di kaki Gunung Lawu, Jokowi pun seharusnya hanya punya satu kata untuk pemerintahannya: Lawan! Dengan satu kata "lawan" itu, ia harus berani melawan siapa saja dan apa saja yang membungkam, memperbudak, menyengsarakan rakyat. Pada kata "lawan" itu, sesungguhnya Jokowi bisa menemukan inti terdalam dari kata kairos.
Jelas laku atau ziarah gunung itu sesungguhnya adalah ziarah rakyat yang bermuatan kairos. Jokowi tak boleh berlambat dengan kairos. Sebab lain dengan waktu biasa, kairos adalah waktu sejarah dan waktu anugerah, karenanya waktu itu takkan berlangsung lama dan hanya datang sekali. Jokowi belum terlambat untuk kembali memeluk kairos itu. Namun, bila berlambat-lambat, dalam sekejap Jokowi akan kehilangan kesempatan menjadi Paku Gunung Jamurdipa bagi Nusantara yang sedang membutuhkannya. Kalau demikian, dalam sekejap Nusantara akan dilanda gonjang-ganjing lagi.
Sindhunata
Wartawan; Penanggung Jawab Majalah Basis Yogyakarta; Kurator Bentara Budaya
* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2015 dengan judul "Jokowi dan Gunung Jamurdipa".
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan