Seperti Apa Sih Scene Film 'Cek Toko Sebelah'? Ini Dia Penuturan Sang Sutradaranya
Film ini bercerita tentang seorang bapak, Koh Afuk (Chew Kin Wah), yang ingin mewariskan toko kepada anaknya.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Ngenest (2015), Ernest Prakasa membuat film lagi, judulnya: Cek Toko Sebelah.
Film ini bercerita tentang seorang bapak, Koh Afuk (Chew Kin Wah), yang ingin mewariskan toko kepada anaknya.
Anak Koh Afuk ada dua—laki-laki semua. Si sulung Yohan (Dion Wiyoko) yang begajulan, dan si bungsu Erwin (Ernest Prakasa) yang kariernya gemilang. Koh Afuk memilih Erwin, intrik pun tercipta.
Kiprah Ernest sebagai filmmaker memang belum terlalu lama. Walaupun begitu, film debutnya, Ngenest, merupakan sebuah drama komedi yang menarik.
Ernest berhasil mengolah buku-bukunya menjadi satu cerita film yang utuh.
Debutnya sebagai penulis skenario (adaptasi) itu pun mengantarkannya menjadi nominee untuk FFI 2016.
CTS akan tayang pada tanggal 28 Desember 2016. Menjelang tibanya film tersebut, Gramedia.com menemui Ernest untuk membicarakan berbagai hal.
Mulai dari ide cerita CTS, alasan Ernest mengangkat kisah seputar etnis Tionghoa, serta pembelajaran yang ia dapatkan selama menjadi sutradara dan penulis naskah.
G: Bisa sedikit diceritakan, awalnya menjadi filmmaker lewat film pertama Ngenest?
E: Kan Ngenest itu kecelakaan nih. Enggak ada rencana nge-direct sama sekali. Awalnya cuma mau nulis sama main. Terus, Pak [Chand] Parwez itu kan emang punya sejarah panjang nyeburin orang gitu.
Kayak Radit [Dika] pertama kali nge-direct juga dia yang kasih kesempatan—begitu juga Fajar Nugros. Istilahnya itu, dia suka buka jalan buat banyak orang.
Nah, dulu itu dia bilang, kenapa gue enggak direct sendiri? Akhirnya, singkat cerita, gue coba.
Setelah menyutradarai Ngenest, gue merasa kepuasannya maksimal. Dan itu mungkin enggak akan terjadi kalau gue hanya menjadi penulis skenario.
Soalnya, salah satu yang enggak enak dari menjadi penulis skenario kan: setelah final draft lo pasrah. Lo enggak bisa apa-apa lagi, karena itu sudah wewenangnya sutradara di lapangan.
Belum nanti wewenang di editor—setelah post-production. Jadi, tahapannya begitu banyak, sehingga walaupun at the end itu nama lo yang tercantum, hasilnya mungkin berbeda dari yang lo tulis.
Nah, menjadi sutradara menurut gue jadi menarik, karena gue bisa menjaga dari hulu ke hilir, agar karya itu utuh—sesuai dengan yang awalnya ingin gue sampaikan.
G: Kapan tepatnya lo berniat untuk membuat film kedua?
E: Jadi begitu Ngenest mendapat sambutan baik, Starvision sudah langsung menanyakan: “Bikin apa lagi nih?” Terus pada waktu itu sih gue bilang, “Nanti aja lah, Pak, belum kepikiran juga mau bikin apa.”
And then, awalnya premis CTS ini mau gue bikin jadi novel sebenarnya. Tapi kalau gue ukur timeline-nya, kayaknya enggak bakal sempat.
Kalau memang gue mau rilis film lagi di akhir tahun, berarti September harus sudah produksi dan sebagainya.
Akhirnya, ya sudahlah, langsung kita bikin skenario aja. Kira-kira selama dua bulan, gue sama istri gue mengembangkan premis CTS sampai ke sinopsis.
Skenarionya sendiri, itu akhir April baru mulai kita develop, kelarnya akhir September.
G: Cek Toko Sebelah berbeda dari Ngenest. Kali ini lo membuat original story baru—bukan adaptasi seperti Ngenest. Kisahnya tentang seorang bapak dua anak yang ingin mewariskan toko. Bagaimana ide itu muncul?
E: Pertamanya, gue belum sampai ke masalah adik-kakak. Awalnya masih tentang orang yang kuliah di luar negeri—yang mana harusnya pendidikan dia baik buat bekal nya ngejar karir—tapi malah ended up jaga toko. Dasarnya itu.
Terus gue riset, ke saudara-saudara gue yang mengalami itu. Cek background-nya, ternyata motivasinya ada macam-macam.
Terus gue merasa masih kurang. Masih ada something missing gitu, konflik utamanya apa? Akhirnya gue tambah sibling di situ.
G: Apakah masih ada kaitannya dengan perjalanan hidup Ernest Prakasa sendiri—seperti halnya Ngenest?
Ini inspirasi dari sekitar sih. Dari keluarga juga. Nyokap gue itu punya toko sembako—dari 1985 sampai sekarang.
Terus banyak kan Chinese yang jauh-jauh sekolah ke luar negeri, baliknya justru jaga toko. Bukan berarti itu sesuatu yang negatif. Tapi ya di balik itu banyak kisah yang menarik.
Begitu juga konflik adik sama kakak, itu juga menarik—dan gue dapat dari sekitar gue. Intinya sih ini pure fiksi, tapi ceritanya amat dekat sama gue.
G: Buat lo, apa bedanya mengadaptasi buku dengan membuat sebuahoriginal story yang baru?
E: Beda banget. Kalau adaptasi, apalagi yang diangkat dari hidup gue, banyak restraint yang enggak bisa gue langgar.
Orang kan ada yang tahu hidup gue, jadi gue enggak bisa mengarang sesuka gue kan. Tapi kalau di CTS ini gue punya kebebasan buat mengarang cerita.
Berdua sama istri gue, kami itu membuat cerita tanpa batasan apapun.
G: Dua film lo sama-sama menyiratkan potret hidup orang Tionghoa. Apa sebab lo memilih itu?
E: Sebenarnya gue enggak punya misi spesifik: “Wah film kedua harus mengangkat cina-cinaan lagi”.
Tapi kebetulan pas gue lagi mencari premis, yang lagi dekat ya itu—untuk sementara.
Enggak tahu kalau ke depannya gue bikin film lagi, apakah masih berkaitan dengan Chinese juga. Jadi memang bukan sesuatu yang diniati.
G: Kita tahu bahwa wacana rasial bisa menuai respons tak terduga—khususnya dari orang-orang yang sensitif. Lo punya pertimbangan tertentu enggak saat mengangkat isu seputar etnis Tionghoa?
E: Enggak sih. Lagian, kalau CTS kan ringan banget ya isunya. Ngenest jauh lebih berat—itu pun enggak ada masalah apa-apa.
Banyak teman gue yang pribumi, setelah menonton Ngenest itu dia malah mikir: “Ternyata gue itu jahat ya. Gue kayak ngerasa bersalah gitu sama temen gue yang Cina.” Padahal gue enggak bermaksud kayak gitu. Tapi kalau akhirnya jadi kritik, ya bagus juga sih [tertawa].
Kalau CTS sendiri, untuk pesan pluralisme dan lain-lainnya, sebetulnya jauh lebih ringan sih. Tetap ada konflik, seperti misalnya yang terjadi pada istri Yohan. Istrinya Yohan itu, Ayu (Ardinia Wirasti), kan pribumi.
Sementara bapaknya Yohan, Koh Afuk kan pernah merasakan kerusuhan 98. Nah, Koh Afuk kurang setuju tuh sama pilihan Yohan menikah sama pribumi. Itu ada, walaupun enggak kita jadikan inti cerita. Itu kita jadikan warna di film ini.
G: Lo sudah berhasil membuat film pertama, merasakan segala proses dan hasilnya. Kira-kira apa yang berbeda dari film kedua lo?
E: Pada saat Ngenest itu gue sama sekali buta soal sinematografi—like literally buta. Gue baca buku.
Tapi hal-hal sesimpel apa efek dari track-in dan track-out aja gue enggak tahu. Co-dir gue pernah nanya, “Ini mau track-in apa track-out?” Gue malah nanya balik, “Apa bedanya?” [Tertawa].
Baru setelah selesai Ngenest gue belajar lagi tuh. Kayak di YouTube kan ada video macem Every Frame is Painting kan—itu gue tonton satu-satu.
Dan dari situ, ternyata gue belajar banyak. Jadi untuk film kedua ini, gue udah ada kemajuan lah. Paling enggak, sekarang gue udah punya visual-treatment.
Gue udah nentuin tracking-nya kayak gimana, detail foreground dan background-nya, dan lain-lain. Semuanya pun ada alasannya.
G: Setelah melalui itu semua, buat lo film yang baik itu kayak gimana sih?
E: Pertanyaannya simpel, tapi jawabnya susah. Gue mungkin jawab dari dua segi kali ya.
Pertama, kalau terkait idealisme, film yang baik adalah film yang hasil akhir sama ide awal itu sejalan. Kayak misalnya gue nonton Selamat Pagi, Malam. Itu menurut gue, Lucky [Kuswandi] dari awal ya pasti membayangkannya begitu—se-raw dan uncomfortable itu.
Kedua, kalau dari segi lebih umum, menurut gue ... Ini beda nih. Biasanya kan sutradara itu paling sebel kalau ditanyakan soal pesan moral.
"Kenapa sih harus ada pesan moral?" Menurut gue, pesan moral itu memang enggak harus. Tapi kan lo bikin sesuatu yang effort-nya minta ampun capeknya, dan berpotensi ditonton jutaan orang.
Kalau bisa ada pesan yang baik, ya why not?
Pewawancara: Raksa Santana/Sumber: Ruang Gramedia
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan




























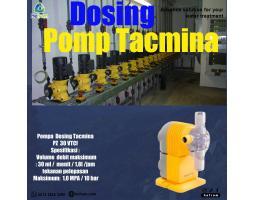

















Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.