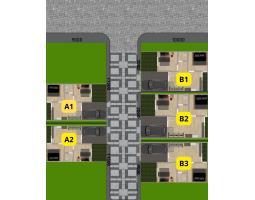Jurnalisme Damai, Mengurai Konflik, Merajut Kebinekaan
Jurnalis tak sekadar memotret kejadian, tetapi adalah seorang produsen realitas sosial
Editor: Yudie Thirzano

Akhirnya, pada 2002, terwujudlah Perjanjian Malino II yang menghentikan konflik tersebut.
Produsen realitas sosial
Belum lama ini, kejadian serupa nyaris meletus di Tolikara, Papua. Isu pembakaran rumah ibadah gencar diberitakan tanpa menyadari dampak negatif yang ditimbulkan.
Bukan menjadi solusi, media massa justru memperkeruh suasana. Namun, hal itu kemudian teratasi.
Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan, peran jurnalis tidak semata-mata melaporkan secara akurat suatu obyek berita untuk kemudian disebarkan.
Jurnalis tak sekadar memotret kejadian, tetapi adalah seorang produsen realitas sosial.
Sebab, apa pun kejadian di luar dunianya dikonstruksikan kembali oleh pikiran, dituangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah "realitas baru".
"Di sinilah letak tanggung jawab jurnalis. Konstruksi realitas yang dibangun oleh seorang jurnalis dapat menjadi 'unit budaya' atau sebaliknya 'sampah budaya' yang ikut menentukan perubahan masyarakat," ujar Imam.
Penyelesaian konflik Poso pada 2002 tak lepas dari peran media massa yang memahami pentingnya perdamaian dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika.
Pemahaman dan penjelasan terkait hal yang sebenarnya terjadi dapat mengurai konflik.
Media massa semestinya tak diam ketika konflik surut.
Upaya pihak yang berkonflik dalam menata kembali lingkungan sekitar juga layak diberitakan sehingga menjadi contoh untuk wilayah lain.
"Karena toleransi bukan sebatas kata-kata atau tulisan. Bukan hanya mau duduk bersebelahan, tapi mau menghidupkan kembali gotong royong antarkelompok yang berbeda," ujar Imam.
Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri M Chandra W Yudha sepakat dengan hal itu. Ia mengatakan, jurnalisme ditujukan untuk membantu masyarakat di wilayah konflik membangun kembali komunitasnya.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan