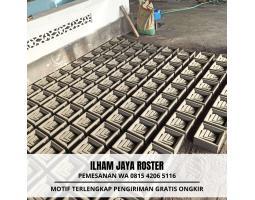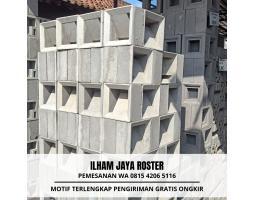Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Ryan Jombang vs Habib Bahar
Perkelahian antara Bahar dan Ryan adalah benturan antara napi berisiko rendah dan napi berisiko sangat tinggi.
Editor: Dewi Agustina

TANPA maksud mengecilkan, kenyataannya kekerasan di dalam penjara bukan satu dua kejadian. Kekerasan dalam penjara merupakan fenomena.
Karena itulah muncul istilah prison culture dan prison mentality. Jadi, duel antara Ryan dan Habib Bahar, jika sebatas ditinjau dari perilaku kekerasannya, bukanlah peristiwa yang luar biasa.
Adu gelut keduanya perlu disorot dari konteks bagaimana sistem peradilan pidana secara terintegrasi menyikapi kedua orang tersebut.
Setiap narapidana menjalani penakaran risiko dan kebutuhan (risk and need assessment) agar dapat diketahui kemungkinan ia mengulangi perbuatan pidananya.
Bahar Smith memperoleh remisi. Itu tentu didahului penakaran risiko dan kebutuhan juga. Jadi, remisi bagi Bahar dapat diartikan sebagai dua hal.
Pertama, pembinaan telah diselenggarakan. Kedua, Bahar merespon positif terhadap program pembinaan.
Dengan kata lain, ringkasnya, pembinaan bagi Bahar berjalan efektif sehingga diyakini kecil kemungkinannya ia akan mengulangi perbuatannya.
Pada sisi lain, Ryan adalah terpidana mati. Ini pun pasti didahului proses ala penakaran risiko dan kebutuhan pula oleh hakim.
Dan ketika hakim menjatuhkan hukuman mati, bahkan bukan hukuman seumur hidup, dapat dimaknai sebagai manifestasi tiga hal.
Pertama, hakim menyimpulkan amat-sangat tinggi peluang si narapidana mengulangi perbuatannya.
Kedua, hakim melihat tidak ada bentuk penanganan (rehabilitasi) apa pun yang akan bisa memperbaiki tabiat dan perilaku Ryan.
Ketiga, hakim merasa berkepentingan untuk juga semaksimal mungkin melindungi masyarakat agar terhindar dari risiko dijahati oleh Ryan.
Dari situ bisa dikatakan, perkelahian antara Bahar dan Ryan adalah benturan antara napi berisiko rendah dan napi berisiko sangat tinggi.
Antara napi yang dinilai tidak lagi membahayakan masyarakat dan napi dengan tingkat kebahayaan maksimal.
Dengan dasar berpikir itu, maka mari kita tinjau beberapa pernyataan sejumlah pihak.
Remisi bagi Bahar patut dicabut.
Tidak. Sekali lagi, kekerasan dalam penjara adalah fenomena. Dan Bahar telah dinilai sebagai napi dengan risiko rendah.
Bahwa Bahar menjadi agresif, tampaknya ada sesuatu yang memprovokasi sedemikian ekstrem yang datang dari lingkungan sekitarnya.
Bahwa Ryan dikabarkan babak belur, ya ini tak lain karena Bahar ternyata lebih kuat dalam benturan tersebut--konsekuensi logis dan alami yang ada pada setiap perkelahian.
Semua pihak yang cedera harus diobati. Perkelahian berikutnya harus dicegah agar tak berulang lagi.
Masukkan Bahar dan Ryan ke dalam satu sel agar silaturahim membaik.
Jangan lupa, subjek yang diperbincangkan ini bukan orang biasa yang hidup bertetangga di kampung halaman yang sama di wilayah yang elok dan permai dengan siulan burung yang berlompatan dari satu pohon ke pohon lain di pagi hari.
Perlakuan terhadap Bahar dan Ryan harus diselenggarakan secara spesifik dan optimal sesuai hasil penakaran risiko dan kebutuhan.
Menyatukan dua napi, padahal mereka memiliki dua tingkat risiko yang berbeda sangat tajam, bukanlah langkah yang terbenarkan.
Tingkat pengamanan terhadap mereka pun harus dibedakan, dengan pengamanan maksimal dikenakan bagi napi yang berisiko sangat tinggi.
Menyatukan napi berisiko rendah dan napi berisiko tinggi ke dalam satu sel justru dikhawatirkan akan menghilangkan efek rehabilitasi yang sudah berlangsung pada diri napi berisiko rendah.
Membiarkan mereka 'bersilaturahmi' di ruang sel yang sama bahkan membahayakan keselamatan napi yang berisiko rendah.
Gesekan antara Ryan dan Bahar patut dibawa ke ranah pidana.
Memang tidak dilarang. Tapi memahami bahwa prison violence merupakan fenomena, maka bagaimana otoritas penegakan hukum juga akan menindak secara pidana pelaku-pelaku perkelahian lainnya di dalam penjara.
Jika pidana hanya dijalankan pada kejadian Ryan vs Bahar, maka boleh jadi sistem penegakan hukum justru akan terkesan bersikap diskriminatif.
Seolah hukum hanya bekerja pada kejadian ini dan abai terhadap kejadian-kejadian serupa lainnya.
Damai sajalah di dalam penjara. Keadilan restoratif, istilahnya. Luka dikasih obat. Rehabilitasi dijalankan lagi agar kerja positif lapas bisa mengendap kembali pada diri napi berisiko rendah.
Satu lagi. Bagi kalangan yang antihukuman mati, menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati dipandang sebagai kekejian yang tak terperi berikutnya.
Di Amerika, pada tahun 1990, rerata masa tunggu antara vonis dan eksekusi adalah 95 bulan. Tapi pada 2019 naik menjadi 264 bulan (22 tahun!).
Tidak hanya masalah bagi terpidana mati. Keluarga korban pun bisa merasakan penderitaan akibat "iming-iming hukum" tak kunjung ditunaikan.
Penulis:
Reza Indragiri Amriel
Dosen dan Ahli Psikologi Forensik


 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan