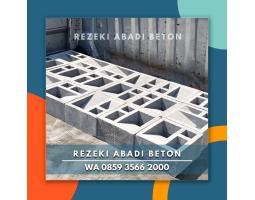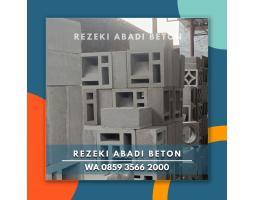Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Beberkan 7 Alasan RUU MK Perlu Dikritik Tajam
Masa lame duck, kata dia, yakni masa di mana pihak-pihak yang sedang sedang berkuasa tengah menghadapi akhir-akhir masa jabatan.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-undang perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) tengah menjadi perbincangan hangat di publik saat ini.
Hal tersebut di antaranya karena dalam rapat di Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Senin (13/5/2024) lalu pemerintah melalui Menko Polhukam dan DPR sepakat untuk membawa RUU tersebut ke dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Hal tersebut lantas memicu kritik dari berbagai pihak baik dari kalangan akademisi hukum tata negara maupun para mantan hakim konstitusi.
Satu di antara akademisi yang mengkritik adalah Guru besar hukum tata negara Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D.
Susi pun membeberkan setidaknya ADA tujuh poin alasan RUU MK tersebut perlu dikritik tajam.
Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara Menilai Revisi UU MK Dilakukan untuk Melumpuhkan Peradilan Konstitusi
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi yang digelar PSHK, STHI Jentera, dan CALS secara daring pada Kamis (16/5/2024).
"Saya melihat, paling tidak ada beberapa poin mengapa pembahasan RUU perubahan ini harus kita kawal dan juga harus mendapat kritik-kritik yang tajam serta dorongan-dorongan yang kuat dari kalangan akademisi, kemudian masyarakat sipil karena ada beberapa hal," kata dia.
1. Argumentasi Terkait Asas Kebutuhan Lemah
Salah satu asas utama dalam pembentukan UU atau perubahan UU, kata dia, adalah asas kebutuhan atau keperluan.
Ia menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan menyangkut asas kebutuhan atau keperluan.
Pertama, lanjut dia, bila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diaelesaikan melalui UU yang saat ini ada.
Kedua, UU yang ada sudah usang.
Baca juga: Badan Legislasi Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR
Ketiga, UU yang ada mengandung materi-materi atau norma-norma yang multi-interpretasi.
Keempat, kata dia, kebutuhan-kebutuhan poltik.
"Inilah yang harus digarisbawahi. Bahwa pembentukan UU atau perubahan UU khususnya yang berkaitan dengan MK harus dihindarkan sejauh mungkin atau malah dibatasi tidak boleh kebutuhan itu karena adanya akomodasi politik atau karena adanya kebutuhan-kebutuhan politik," kata dia.
"Mengapa demikian? Karena itu akan dikaitkan dengan fungsi MK sebagai pihak ketiga netral ketika terjadi persoalan-persoalan atau sengketa antara warga negara dengan negara," sambung dia.
2. Tidak Patut Dilaksanakan pada Masa Lame Duck
Masa lame duck, kata dia, yakni masa di mana pihak-pihak yang sedang sedang berkuasa tengah menghadapi akhir-akhir masa jabatan.
Menurutnya, meski kekuasaan tersebut masih mempunyai legitimasi di masa tersebut, namun di antara mereka akan ada orang-orang yang tidak akan berkuasa lagi pada periode berikutnya di antaranya karena tidak terpilih lagi.
"Maka secara fatsun politik seharusnya mereka tidak mengambil keputusan-keputusan yang akan memberikan dampak yang luas krpada pemerintahan dan juga masyarakat di masa yang akan datang," kata dia.
3. Minim Partisipasi Bermakna

Menurutnya, tidak ada dokumen yang dapat diakses terkait RUU tersebut.
"Apalagi keterlibatan secara aktif dari masyarakat (dinyatakan) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 96 a UU 13/2002 yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan," kata dia.
4. Materi Muatan RUU yang Dapat Melemahkan Independensi
Secara substansi, menurutnya RUU tersebut memuat sejumlah hal yang dapat melemahkan independensi MK di antaranya masa jabatan hakim dari 15 tahun menjadi 10 tahun.
Selain itu juga, pasal 23 A yang dapat ditafsirkan maknanya lembaga pengusul hakim konstitusi (presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi.
Baca juga: Penampakan Rumah Mewah dan Mobil Mercy SYL yang Disita KPK
Selanjutnya, ketentuan peralihan tersebut diberlakukan surut.
Kemudian, kata dia, juga terkait dengan keterlibatan lembaga pengusul dalam penentuam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Selain itu, kata dia, ketentuan di mana hakim konstitusi tetap menjadi anggota MKMK.
"Persoalannya adalah bagaimana kemudian hakim konstitusi juga diadukan sebagai diduga melakukan pelanggaran etik. Apakah itu lagi-lagi tidak terjadi conflict of interest?" kata dia.
5. Proses Bermasalah Secara Internal
Menurutnya dari pemberitaan diketahui bahwa kesepakatan antara pemerintah dan DPR dilakukan di masa anggota DPR reses secara sembunyi-sembunyi.
"Kemudian bagaimana anggota-anggota Komisi III itu juga banyak yang tidak hadir. Oleh karena itu secara internal pembahasan RUU ini pun bermasalah. Dalam arti apa? Tidak semua anggota yang terlibat di dalamnya itu ikut serta dalam pembahasan bahwa RUU ini akan disetujui dibawa pada rapat Paripurna," kata dia.
6. Lemahnya Jaminan Terkait Masa Jabatan Hakim Konstitusi (security of teneur)
Terkait lemahnya jaminan masa jabatan hakim, menurutnya meskipun MK mengatakan bahwa usia jaminan masa jabatan merupakan open legal policy (kewenangan pembentuk Undang-Undang), tetapi menurutnya kewenangan tersebut perlu dibatasi.
"Mengapa security of teneur ini menjadi penting? Karena security of teneur ini menjadi salah satu jaminan dari independensi hakim maupun pengadilan," kata dia.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Komitmennya soal Demokrasi saat Pimpin RI: Saya Sudah Keluar Militer 25 Tahun
Ia memandang jaminan terkait masa jabatan hakim tersebut kerap diotak-atik karena jaminan independensi di dalam UUD 1945 adalah jaminan independensi yang bersifat sangat minimal.
"Dan jaminan itu membutuhkan bantuan badan-badan eksternal di luar pengadilan untuk menegakannya," kata dia.
"Dalam kaitan ini UUD 1945 tidak secara spesifik mengatakan bahwa bagaimana security of teneur itu dijamin, bagaimana syarat-syarat menjadi hakim itu juga dijamin di dalam UUD," sambung dia.
7. Cawe-cawe Politik dalam Indepensi Lembaga Kehakiman (court packing plan)
Terkait dengan cawe-cawe politik terhadal independensi hakim, ia mengemukakan sejarah yang mencatat upaya intervensi politik secara terselubung terhadap independensi lembaga kehakiman.
Upaya tersebut, kata dia, pernah terjadi melalui RUU Reformasi Prosedur Peradilan di Amerika Serikat pada tahun 1937 atau yang lebih dikenal dengan "court packing plan".
Sejarah mencatat strategi court packing tidak dapat dilepaskan dari hasrat Presiden AS saat itu Franklin D Roosevelt untuk melakukan penambahan jumlah hakim di Mahkamah Agung AS guna mendapat persetujuan terhadap serangkaian kebijakan Rooosevelt yang disebut Undang-Undang New Deal.
Namun, dalam konteks RUU MK saat ini strategi court packing tersebut harus ditafsirkan lebih luas dari hanya sekadar menambah jumlah hakim.
"Tetapi, juga termasuk setiap usaha memanipulasi keanggotaan hakim untuk tujuan yang bersifat partisan. Ini adalah isu kedua yang juga harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati," kata dia.
"Jangan sampai ketentuan pasal 23(A) itu merupakan court packing yang terselubung dari pembentuk UU. Karena apa? Karena itu merupakan usaha untuk memanipulasi keanggotaan hakim, membership dari hakim di sebuah pengadilan. Untuk tujuan apa? Yaitu untuk tujuan yang bersifat partisan," sambung dia.
Menurutnya, ketentuan dalam pasal 23A RUU MK dapat ditafsirkan maksudnya adalah agar lembaga pengusul hakim konstitusi (presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) dapat mengevaluasi hakim konstitusi yang mereka tunjuk.
Oleh karena itu, ia khawatir ketentuan pasal 23A dalam RUU MK dapat menjadi praktik court packing terselubung yang dapat dimanfaatkan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Lembaga pengusul hakim konstitusi dikhawatirkannya dapat menggunakan ketentuan dalam pasal 23A RUU MK untuk melakukan pembalasan terhadap hakim-hakim konstitusi yang sudah menjatuhkan putusan atau menyatakan dissenting opinion yang tidak disukai oleh pihak-pihak yang mengusulkan.
"Oleh karena itu, ketika akan dilakukan evaluasi maka pertanyaan kita poin-poin, standard, atau ukuran apa yang akan digunakan oleh lembaga pengusul itu dalam rangka melakukan evaluasi. Dalam pandangan saya evaluasi ini tidak dilakukan oleh setiap lembaga pengusul?" kata Susi.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan