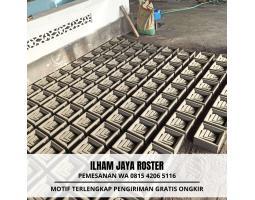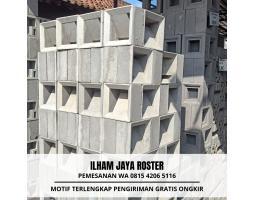Kisah Transmigran Bali dari Mual Keracunan Umbi Gadung hingga Akulturasi
Bagaimana mereka melakukan akulturasi budaya dan menyatukannya dengan budaya warga asli? Ini kisahnya.
Editor: Robertus Rimawan

Laporan Waratwan Tribun Bali, Luh De Dwi Jayanthi
TRIBUNNEWS.COM, BANGGAI - Transmigran Bali di Sulawesi Tengah tetap menjunjung tinggi tradisi dan budaya agama Hindu meski berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.
Bagaimana mereka melakukan akulturasi budaya dan menyatukannya dengan budaya warga asli?
Masyarakat Desa Kospa Dwata Karya, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), ini merupakan sebagian kecil warga Bali yang bertransmigrasi ke luar daerah.
Transmigran yang kini menetap di sana berawal dari program transmigran tanpa biaya bantuan (TBB) asal Kabupaten Tabanan, Bali, tahun 1972 sebanyak 96 kepala keluarga (KK).
Penulis sejarah transmigran di Desa Kospa Dwata Karya, I Made Ngarsa, mengatakan, saat itu transmigran dari Bali disambut oleh kepala daerah tingkat II Banggai untuk penyerahan 250 hektar tanah untuk 100 KK.
“Sebelum menebang pohon di hutan, terlebih dahulu melaksanakan Upacara Adat Masama yaitu potong kambing dan ayam untuk memohon izin pembangunan pemukiman,” terang Ngarsa, Minggu (20/9/2015).
Transmigran saat itu hanya berbekal nasi onot (umbi gadung), mereka mulai merambah hutan meskipun sering merasakan mual dan muntah.
“Saat kami kerja buka kebun baru sering mengalami keracunan nasi onot. Tapi bagaimanapun kami harus tetap bekerja keras di bawah terik matahari dan hujan demi mewujudkan cita-cita. Ya, meskipun nafas sudah tersengal-sengal,” ujar Ngarsa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 1996-2001 ini.
Dari sana sudah mulai muncul perbedaan antara transmigran mengenai kondisi fisik serta pengalaman.
“Ada kelompok asal Wangaya dan Sangketan yang sudah beradaptasi dengan lingkungan hutan, sedangkan kelompok asal Perean, Luwus dan Petiga mengenal hutan baru sampai Sulawesi,” tutur Ngarsa.
Keadaan seperti itu melahirkan kehidupan yang berkelompok-kelompok dari tahun 1972-1974.
Ngarsa menuturkan, perbedaan kelompok ini memengaruhi adat istiadat di Desa Kospa Dwata Karya saat itu.
“Ini yang paling sulit, hampir di antara kita terjadi kesalahpahaman. Sempat terjadi cara pandang yang senjang, perlu waktu untuk membaurkan kelima adat yang berbeda ini,” ujarnya sambil mengerutkan dahinya.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan