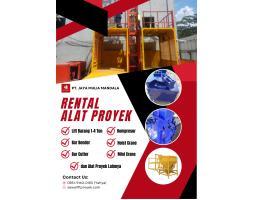Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menjadi Perempuan Indonesia dan Emansipasi Setengah Hati
Menjadi perempuan Indonesia itu rasanya seperti menjadi warga kelas dua di negeri sendiri. Kita, kaum perempuan, rasanya tidak pernah benar-benar dian

Ditulis oleh Tribunners, Esmasari Widyaningtyas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi perempuan Indonesia itu rasanya seperti menjadi warga kelas dua di negeri sendiri. Kita, kaum perempuan, rasanya tidak pernah benar-benar dianggap sejajar apalagi setara dengan laki-laki. Kita berada di dalam dunia laki-laki. Dunia, dimana kebanyakan norma dan aturannya lebih menguntungkan kaum laki-laki.
Silahkan saja kalau mau menyebut saya pesimis, tapi begitulah kenyataannya. Saya tidak menampik kenyataan, bahwa memang betul setelah melalui perjuangan ratusan tahun, perempuan Indonesia sekarang bisa memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan formal setinggi-tingginya. Dan tidak salah pula, bahwa ratusan tahun setelah Kartini mengeluarkan uneg-unegnya melalui surat-surat kepada Nyonya Abendanon, perempuan Indonesia kini berpeluang untuk memiliki karir cemerlang diluar rumah. Lihatlah para CEO perempuan itu, atlet-atlet perempuan, tentara dan polisi perempuan, lihat pula para menteri-menteri perempuan itu dan politisi perempuan.
Emansipasi setengah hati
Diatas kertas laki-laki dan perempuan seolah setara, punya kesempatan yang sama. Begitukah? Kenyataannya, perempuan hampir selalu memiliki hambatan lebih besar saat ia berusaha mencapai cita-citanya ketimbang laki-laki. Perempuan yang sukses karirnya, tinggi pendidikannya kerap dibayang-bayangi oleh pandangan sinis sebagian masyarakat. Dianggap tidak becus mengurus rumah lah, dinilai menelantarkan keluarga lah, bahkan ada pula yang menilai pencapaian seorang perempuan hanya bisa diperoleh karena kemolekan tubuh atau kecantikannya. “Ah, dia sih bisa dapat promosi karena ngerayu bos. Diajak makan, ini itu.”
Akui saja, pergunjingan seperti itu pernah sampai ke telinga Anda bukan? Kenapa perempuan tidak bisa dihargai karena kemampuannya saja? Kenapa keberhasilannya harus disangkut pautkan dengan urusan fisik?
Di atas kertas, emansipasi terdengar manis. Perempuan Indonesia sukses mewujudkan emansipasi! Ada kuota 30% perwakilan di badan legislative, hebat! Lantas apa? Apakah serta merta hal itu mengubah nasib dan kedudukan kita sebagai seorang perempuan. Nyatanya, aturan yang dibuat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik itu tidak mudah dipenuhi. Masyarakat kita masih terpaku pada pemikiran kuno bahwa politik bukanlah dunia perempuan.
Realitas di lapangan, proses rekrutmen politisi perempuan oleh partai-partai politik itu tidak lebih dari sekedar dagelan. Demi keuntungan pragmatis, kemenangan suara terbanyak dalam election, Parpol lebih suka merekrut calon legislator perempuan yang cantik, yang bersuara merdu, bertubuh aduhai dan lebih bagus lagi kalau berduit. Urusan kemampuan, kinerja dan integritasi soal belakangan. Itukah yang kita sebut emansipasi?
Perempuan itu objek
Perempuan Indonesia masih kerap dipandang sebagai objek. Kita ini objek politik, objek kekerasan, objek seksual. Kita terkurung dalam sangkar emas yang disebut emansipasi. Dan bodohnya, ini tidak pernah benar-benar kita sadari. Pemikiran, dan cara pandang kita mengenai peran perempuan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat di era Kartini.
Memang betul, ada banyak perbaikan disana-sini. Ada banyak peluang yang disediakan buat perempuan, tapi cara pandang kita masih sama. Coba saja tanyakan orang-orang di luar sana, apa tugas utama perempuan? Sebagian besar, saya yakin, bakal menjawab melahirkan, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami. dan sebagainya. Aapapun perannya diluar rumah. Perempuan harus kembali ke “kodrat” nya untuk menjadi ibu dan istri.
Hal itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Bukankah rumah tangga itu dibangun atas kerjasama suami dan istri? Kalau begitu kenapa persoalan mengurus rumah dan anak hanya menjadi domain perempuan seorang? Bukankah itu seharusnya ditanggung bersama oleh partner hidupnya? Mengurus anak? Ya itu tugas suami dan istri. Mengurus rumah? Itu juga tugas suami dan istri. Kalau perempuan seringkali dibebani untuk mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga, kenapa beban yang sama, yaitu mengurus rumah dan anak tidak bisa dibebankan pula kepada laki-laki? Bukankah laki-laki dan perempuan setara?
Karena perempuan masih kerap dijadikan objek, itulah sebabnya mengapa kita masih kerap menjadi korban kekerasan dan pelecehan oleh laki-laki. Seolah belum cukup, perempuan-perempuan tak berdaya ini nanti juga harus menjadi korban dari lingkungan sosial dan bahkan tak jarang pula dari penegak hukum. Saya nggak tahu apa yang salah dalam masyarakat kita, tapi perempuan-perempuan korban kekerasan dan pelecehan ini malah kerap disalahkan atas musibah yang menimpa mereka. “Ah, pantas saja dilecehkan, dia naik angkot sendirian, malam-malam pula!”
Lho? Bukankah ini masa dimana perempuan seharusnya dianggap sejajar dengan laki-laki. Kalau begitu, perempuan juga seharusnya berhak untuk memiliki kebebasan yang sama dong seperti laki-laki. Perempuan berhak atas rasa aman menaiki kendaraan umum. Kita juga berhak atas rasa aman saat pulang kerja larut malam. Kenapa perempuan harus dibayang-bayangi ketakutan akan diperlakukan jahat oleh laki-laki berotak sampah. Jadi dimana emansipasi yang selama ini dibanggakan itu?
Terbitlah terang
Ah, saya pikir,cita-cita Kartini tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pun tidak hanya sebatas pada persoalan kesetaraan tingkat pendidikan sajalah. Kalau cuma itu, betapa dangkalnya pemahaman tentang emansipasi. Kartini itu seorang revolusioner, ya saya menyebutnya begitu. Karena pemikirannya yang kritis ia bisa memahami bahwa ada ketimpangan peran dan hak laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial masyarakat. Dia mencermati itu, dia menilai ada yang harus diperbaiki. Itu sebabnya ia mengupayakan pendidikan untuk perempuan. Tujuannya agar perempuan terbuka pemikirannya. Agar mereka berani memberdayakan pikirnya, mendobrak cara pandang kuno dan berani berpikir kritis.
Inilah tantangan terbesar kita dalam memperjuangkan emansipasi yang sebenarnya. Mengubah cara pandang kita mengenai perempuan. Agak lucu sebenarnya, bahwa setelah ratusan kali kita merayakan Hari Kartini setiap tahun, ternyata masih ada saja perempuan yang mengukur keberhasilan perempuan lainnya berdasarkan status pernikahan, sudah melahirkan atau belum, anaknya dekil atau nggak.
Hal yang agak menggelikan sebenarnya, ketika seorang perempuan dianggap tidak sukses hanya karena ia belum menikah, atau belum memiliki anak. Penilaian model begini biasanya hanya ditujukan buat perempuan, tapi tidak dengan laki-laki. Ironis sebenarnya, karena diskriminasi perempuan ini juga dilakukan oleh perempuan sendiri. Sekali waktu saya juga menjumpai ibu-ibu dengan komentar dan pandangan yang tidak pro emansipasi. “Lho, anak cowok kok disuruh sapu rumah? Kok cuci baju sendiri? Itu kan kerjaan perempuan?
Ya Tuhan!
Masyarakat kita memang telah mengalami degradasi nilai-nilai sosial yang luar biasa, terutama terhadap cara pandangnya mengenai perempuan. Di era kerajaan dulu, sebut sajalah era Mataram, Medhang, Singasari hingga Majapahit, perempuan dipandang sebagai sosok agung. Itulah kenapa orang-orang jaman dulu punya banyak dewi untuk dipuja.
Perempuan, terutama ibu, punya peranan penting. Perempuan adalah simbol pemberi kehidupan. Itu sebabnya mengapa mereka menyebut bumi sebagai ibu pertiwi. Karena sifat-sifatnya seperti seorang ibu. Tangguh, kokoh, dan sabar. Meski kerap dipijak, tapi ibu pertiwi tidak pernah berhenti menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai sumber makanan, obat-obatan. Itulah kenapa penghormatan terhadap ibu pertiwi demikian besar di masa lalu. Perlu ada ritual saat tanam padi, ada doa yang dipanjatkan saat musim panen dan tidak ada yang berani melakukan pengrusakan pada ibu pertiwi.
Leluhur kita bahkan mengenal kesetaraan gender sejak lama. Itu sebabnya mereka memiliki konsep lingga dan yoni sebagai simbol keseimbangan.
Sungguh, perempuan Indonesia memiliki potensi untuk memajukan bangsa ini. Kita mungkin perlu memulainya dengan mengubah cara pandang kita terlebih dulu mengenai perempuan. Kita perlu paham bahwa perempuan membutuhkan lebih dari sekedar kesetaraan tingkat pendidikan. Kita memerlukan perlakuan yang adil dan setara dengan laki-laki. Perempuan seharusnya tidak lagi dinilai berdasarkan stereotype masa lalu yang lebih mengedepankan masalah fisik dan urusan domestik semata.
Satu hal konkrit yang bisa kita lakukan sebagai perempuan Indonesia adalah mendidik generasi penerus yang berkualitas. Tidak hanya memiliki kepandaian tapi juga kepekaan sosial. Ini bukan peran yang sepele. Ini persoalan keberlangsungan Indonesia untuk puluhan bahkan ratusan tahun mendatang. Semoga dengan peran aktif kita sebagai perempuan yang kritis dan berdaya, kita bisa membawa bangsa ini menjadi lebih tercerahkan. Habis gelap terbitlah terang.


 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan