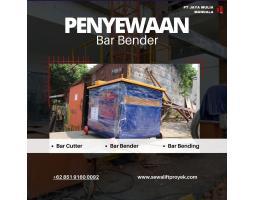Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Rahasia di Balik Pesantren Berwajah Etnik, Yang Wajib Anda Ketahui
Tidak jarang karya arsitektur tersebut dihasilkan dari upaya-upaya serius untuk menggabungkan aspek Islam.
Editor: Husein Sanusi
Rahasia di Balik Pesantren Berwajah Etnik, Yang Wajib Anda Ketahui
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA
TRIBUNNEWS.COM - Setiap tamu yang datang ke Bina Insan Mulia, langsung disambut oleh bangunan-bangunan berwajah etnik. Mulai dari pagar, asrama santri, kelas, tempat-tempat belajar santri, furnitur, dan ornamen. Bahkan rumah yang saya tempati bersama keluarga juga menggunakan bahan-bahan etnik.
Tidak sedikit benda-benda etnik pedesaan tempo dulu diubah fungsinya di Bina Insan Mulia karena pertimbangan estetika. Misalnya lesung yang dulunya untuk menumbuk padi dijadikan tempat duduk para santri saat belajar. Atau dipakai pajangan di sudut-sudut bangunan. Kandang sapi atau kuda diubah fungsinya menjadi garasi mobil.
Bangunan yang unik tradisional, seperti rumah limasan, rumah joglo, atau rumah gladak, menjadi tempat kegiatan belajar, dan tempat tinggal atau asrama. Ruangan dan kamar-kamar santri sengaja tidak diamplas atau diaci untuk memperkuat aspek naturalnya dan seninya. Di samping itu juga untuk memperkuat paduan antara kayu, batu bata merah, batu alam, dan material lainnya.
Sejak 2015, saya memang terus memburu informasi ke beberapa daerah untuk mendapatkan berbagai material bangunan yang berbasis etnik. Alhamdulillah, saya menemukannya di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur danJawa Tengah
Setelah terjadi kesepakatan, materialnya diangkut ke Cirebon. Tentu tidak sembarangan untuk mengangkutnya. Setelah sampai di Cirebon, tidak sembarang tukang juga bisa mengerjakan itu. Tukangnya harus tukang khusus kayu. Demikian juga dengan asistennya.
Kualitas kayunya variatif dengan rata-rata usia puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1 abad. Pembangunan pesantren berwajah etnik terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan santri dan wali santri.
Beberapa bangunan erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa penyebaran Islam di Indonesia meninggalkan banyak warisan. Tidak saja sistem hidup seperti yang kita jalankan saat ini, tetapi juga karya arsitektur. Mulai dari rumah, tempat berkumpul, dan tempat ibadah.
Tidak jarang karya arsitektur tersebut dihasilkan dari upaya-upaya serius untuk menggabungkan aspek Islam yang notebene dari luar dengan aspek budaya lokal. Contoh paling nyata adalah masjid Demak yang merupakan masjid tertua di Indonesia.
Corak bangunannya mengusung khas Majapahit yang bersumber dari Hindu Bali. Demikian juga atapnya dan lengkungan di dalamnya. Nampak sekali para wali tidak sekedar membuat bangunan, tetapi beliau-beliau itu berkarya dengan intelektual dan spiritual yang tinggi.
Hingga hari ini, menurut informasi yang saya dapatkan dari kalangan wartawan, Pesantren Bina Insan Mulia menjadi pesantren berwajah etnik terbesar di Indonesia hari ini. Terlepas dari itu, sesungguhnya apa yang saya maksudkan dengan bangunan-bangunan berwajah etnik tersebut memang bukan soal seni semata atau bukan soal pelestarian karya arsitektur semata.
Yang sangat mendasar adalah nilai-nilai pendidikan yang diperjuangkan oleh Pesantren Bina Insan Mulia, yaitu pendidikan budaya. Para santri dididik dengan penanaman pemahaman dan nilai-nilai yang berbasis budaya sehingga dakwah Islamnya menjadi dakwah yang rohmatan lil alamin.
Pesantren dan Pendidikan Budaya
Jujur saja, pesantren termasuk lembaga terdepan dan yang paling peduli untuk urusan pelestarian budaya. Cuma memang jarang pemerintah atau sebagian masyarakat melihatnya dari aspek itu. Malah pesantren pernah dicap dengan stempel yang tidak-tidak. Sarang teroris lah, radikal lah, atau anti NKRI lah.
Apa bukti pesantren itu sangat peduli pada budaya? Sejak ratusan tahun lalu, pesantren telah menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tingkat tinggi untuk menerjemahkan kitab yang berbahasa Arab.
Dan sampai saat ini, pesantren yang tetap menggunakannya tetap ada meskipun jumlahnya terus berkurang. Kenapa kok berkurang? Ini bukan tugas pesantren, tetapi tugas kementerian pendidikan: kenapa semakin banyak bahasa daerah yang tergerus oleh perubahan zaman. Padahal bahasa menjadi salah satu modal sosial dan menunjukkan eksistensi bangsa.
Bahkan bahasa sehari-hari yang digunakan di pesantren untuk menjelaskan hubungan antara guru, santri, dan kiai itu bahasa Jawa yang tinggi. Bagaimana di tempat lain? Misalnya di Banten, di Cirebon, di Sumatera, di Kalimantan, di NTB, atau di Aceh? Sama juga. Masyarakat pesantren memilih tingkat bahasa yang tinggi untuk berkomunikasi.
Percakapan antara KH. Hasyim Asy a’ri dan KH. Wahid Hasyim tetap menggunakan bahasa Jawa yang tinggi meskipun beliau berdua lama di Mekkah. Bahkan Kiai Marzuqi Lirboyo tidak menggunakan bahasa Jawa kelas awam untuk berbicara dengan santrinya. Beliau menggunakan bahasa Jawa kromo alus dengan para santrinya untuk menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan soal bahasa verbal semata, tetapi mengandung tata krama.
Itulah yang dicontoh para kiai dalam melestarikan budaya. Selain bahasa dan tata krama, pesantren juga melestarikan produk budaya lain, yaitu pakaian. Saya kemana-mana menggunakan sarung, kemeja, kopyah dan sandal. Lucunya, ketika saya masuk beberapa kota, justru saya yang dibilang ganjil secara budaya, padahal inilah budaya asli kita.
Kopyah dan sarung itu sejatinya tidak identik Islam tapi Nusantara. Lihat, di zaman Pak Harto dulu, semua pejabat pakai kopyah keman-mana, apalagi pada acara-acara resmi. Demikian juga sarung. Bagi orang Aceh, Jawa Barat, Betawi atau di beberapa tempat lain, sarung itu bukan untuk shalat saja. Pagelaran budaya yang mereka atraksikan di panggung juga menggunakan sarung.
Contoh-contoh sekilas di atas hanyalah sebagian kecil dari perhatian pesantren terhadap pendidikan budaya. Apa sejatinya pendidikan budaya di pesantren, khususnya di Bina Insan Mulia?
Sebagaimana sudah diketahui umum, budaya adalah tata cara hidup yang diciptakan manusia dalam sebuah masyarakat dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu. Dalam perjalanannya, budaya itulah yang menjadi karakteristik atau ciri khas utama masyarakat tersebut.
Budaya Bali berbeda dengan budaya Sunda dalam beberapa hal. Budaya Arab berbeda dengan budaya Nusantara dalam beberapa hal. Budaya Barat berbeda juga dengan kita. Masyarakat membangun budaya dari generasi ke generasi lalu menjadi kode sosial. Budaya kemudian menjadi identitas, bahkan menjadi kekayaan suatu masyarakat.
Tata cara hidup yang disebut budaya itu kemudian oleh sebagian ahli dijabarkan ke dalam unsur-unsur budaya. Secara umum, unsur budaya mencakup antara lain: a) sistem dan adat istiadat keagamaan, b) sistem dan organisasi kemasyarakatan, c) sistem pengetahuan, d) bahasa, e) kesenian, f) sistem mata pencaharian hidup, dan g) sistem teknologi dan peralatan.
Apa hubungannya dengan pesantren? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam. Sudah pasti keislaman menjadi karakteristik utama. Lalu kenapa harus ada budaya?
Hubungan antara Islam dan budaya memang sangat luas, multi dimensi, dan tidak bisa dijelaskan secara hitam-putih, haram-halal. Namun, untuk konteks pendidikan budaya di Pesantren Bina Insan Mulia, saya hanya ingin menjelaskan beberapa poin saja untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman budaya sebagai dukungan terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan keislaman dalam masyarakat.
Budaya adalah produk dari manusia, sedangkan agama adalah produk dari Allah SWT atau wahyu. Apakah keduanya harus dipertentangan atau dipertemukan atau dikerjasamakan? Jawabannya jelas tergantung.
Untuk budaya yang positif atau budaya yang baik, budaya tersebut harus diikutkan sekalipun untuk pelaksanaan ibadah yang formal (mahdhoh). Shalat itu yang isinya dari agama terdapat pada gerakan, ucapan, dan aktivitas hati lalu tanah untuk bersujud dan penutup aurat secukupnya. Sisanya dimainkan oleh faktor-faktor budaya. Misalnya sarung, pakaian, masjid, tempat wudhu, kopyah, serban, atau pengeras suara.
Demikian juga puasa. Yang heboh di Indonesia itu bukan unsur agama dalam puasa Ramadhan, tapi lebarannya atau menunya atau hubungan antara momen puasa Ramadhan dan dampak ekonominya. Demikian juga haji. Aspek ajaran agamanya sedikit sekali. Sisanya adalah kebutuhan yang muncul dari budaya, mulai paspor, tes kesehatan, hotel, makan, pakaian, dan lain-lain.
Bahwa seringkali konsentrasi pada pemenuhan kebutuhan budaya lebih menyita perhatian umat beragama ketimbang tuntutan ajaran, memang ini perlu dikoreksi bersama. Jangan sampai esensi ibadah formal itu hilang di tengah hiruk pikuk perayaan budaya.
Bagaimana penerapan pendidikan budaya dalam bermuamalah antarmanusia? Menurut saya, di sinilah poin utamanya. Kenapa? Ibadah muamalah adalah ibadah yang dinamis sehingga pemahaman budaya sangat diperlukan. Pemahaman tersebut tentu diperoleh dari pendidikan budaya.
Terkait dengan ibadah muamalah ini, Islam sedikitnya memiliki 4 sikap. Pertama, ada budaya yang malah dianjurkan karena memang mendukung pelaksanaan ibadah muamalah tersebut. Misalnya shodaqoh dalam berbagai bentuk, seperti menolong orang, memberi pinjaman, memberi makan, menjamu tamu, dan seterusnya.
Sejak zaman Firaun atau sejak dahulu kala, semua bangsa di dunia ini punya budaya tersebut. Oleh Islam malah diperkuat. Rasulullah SAW banyak memberikan apresiasi kepada orang yang suka menolong orang. Sebaliknya, orang yang enggan bersedekah atau tidak mau peduli malah dibilang sebagai orang yang mendustai agamanya, seperti dalam Surah Al-Ma’un ayat 1-7:
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya. Yang berbuat ria. Dan enggan (memberikan) bantuan.”
Kedua, ada budaya yang dikoreksi oleh Islam lalu dilanjutkan, misalnya nikah lebih dari empat atau aturan Islam mengenai perkawinan sedarah. Dulu orang menikahi perempuan semaunya. Islam hadir untuk memberikan batasan. Demikian juga pernikahan sedarah yang dulu menjadi tradisi orang-orang kelompok tertentu. Oleh Islam kemudian dikoreksi.
Ketiga, ada budaya yang memang dipadukan seperti dilakukan oleh Wali Songo. Masjid Menara Kudus adalah salah satu simbol adanya akulturasi budaya tersebut. Bodi masjid mensimbolkan candi, tapi atapnya mensimbolkan Islam, sedangkan pancuran wudhunya mensimbolkan Budha.
Keempat, budaya yang memang ditentang oleh Islam karena merusak akal, keturunan, agama, dan harta benda, seperti minum-minuman keras, free seks, judi, dan penyembahan berhala.
Dengan penjelasan seperti di atas, maka hemat saya, inti dari pendidikan budaya di pesantren adalah bagaimana para santri dapat menghadirkan Islam sesuai karakteristik masyarakat yang dimasuki, seperti para nabi atau Wali Songo di Nusantara. Caranya fleksibel dan sangat “human” namun secara esensi tidak berkurang sedikit pun.
Di samping itu, dengan adanya pemahaman mengenai budaya, maka para santri akan memiliki kecerdasan budaya. Maksudnya, mereka bisa membedakan mana budaya yang dibutuhkan, digabungkan, ditentang total atau dikoreksi. Jangan sampai serba mengharamkan budaya atau serba membolehkan.
Hal lain yang menjadi inti dari pendidikan budaya adalah agar para santri Bina Insan Mulia terus berkembang sesuai perubahan masyarakat dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai ketinggalan zaman atau menolak perubahan zaman. Pesantren Bina Insan Mulia langsung memberikan contoh atau praktik. Misalnya, semua kegiatan dakwah di Bina Insan Mulia sekarang ini, dari mulai kegiatan santri, kegiatan guru, dan kegiatan saya, akan di-upload di media sosial.
Pendidikan budaya di Pesantren Bina Insan Mulia juga menghantarkan para santri untuk mengakses berbagai kearifan lokal untuk memperkaya pemahamannya mengenai kehidupan. Pemahaman keagamaan yang dipadu dengan kearifan akan menjadi modal penting untuk menghadirkan Islam Tengah atau Islam Moderat atau Islam Wasatiyah.
Hal lain yang sangat penting lagi adalah pendidikan budaya di Pesantren erat kaitannya dengan soal etika atau adab wal akhlak. Islam sudah memberikan panduang bagaimana akhlak dan adab, tetapi praktiknya diserahkan pada budaya lokalnya.
Misalnya berbuat baik atau sopan pada orang tua. Ini ajaran Islam, tetapi bagaimana ekspresi dan aktualisasi dari sopan dan berbuat baik itu tentu menyesuaikan budaya setempat. Ukuran sopan di Arab Saudi berbeda dengan ukuran sopan di Jawa Barat meskipun ada hal-hal prinsip yang sama.
Itulah gambaran mengenai pentingnya pendidikan budaya.
Wujud Pendidikan Budaya di Bina Insan Mulia
Pendidikan budaya di Bina Insan Mulia tidak disampaikan secara berteori melalui mata pelajaran khusus, tetapi disajikan ke dalam tiga wujud.
Pertama, melalui ide, konsep, atau pemikiran dengan segala bentuk turunannya. Saya dan para tamu yang saya undang, selalu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana santri Bina Insan Mulia nanti berkembang sesuai kemajuan zaman di satu sisi, namun tetap harus menjaga karakteristik ke-Islaman dan ke-Indonesiaan di sisi lain. Demikian juga prinsip dasar NU yang mengamalkan Islam secara tawasud, tawazun, dan tasamuh itu selalu kami sampaikan.
Kedua, pendidikan budaya juga disajikan melalui kreativitas secara fisik. Misalnya, saya menerima tamu dari berbagai kalangan. Itu adalah pendidikan budaya yang nyata. Orang berjubah saya terima, orang geng motor saya terima, orang berdasi saya terima, tokoh politik saya terima, kiai tarekat saya terima, dan seterusnya.
Kemampuan mengakomodasi keragaman adalah bagian penting dari pendidikan budaya dan agama sekaligus. Mewadahi keragaman tidak sama dengan ketidakjelasan. Kita diperintahkan harus berprinsip di satu sisi, namun harus fleksibel di sisi lain. Dari sinilah lahir toleransi yang sehat dan cerdas.
Bahkan, cara hidup di Bina Insan Mulia juga mengakomodasi tak terhitung keragaman. Satu sisi para santri mengamalkan praktik-praktik salaf, misalnya menggunakan kopyah, puasa, mencium tangan guru-guru, bahkan mematung kepada kiai-kiai dan tamunya. Namun, di sisi lain sangat adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sengaja saya kumpulkan mobil-mobil yang katanya mewah atau teknologi canggih, seperti smart class atau makanan barat di Bina Insan Mulia 2. Semua itu sesungguhnya untuk mengisi materi pendidikan budaya. Satu sisi mereka perlu menerima perubahan dan perkembangan zaman, tapi di sisi lain punya komitmen kuat untuk mempertahan jati diri.
Acara haul setiap tahun pun dikemas dengan memadukan unsur agama dan budaya. Ada istighosah, tahlil, dan tahfidz, tapi juga ada pagelaran seni budaya. Bahkan saya mengundang artis ibu kota untuk menghibur santri dan masyarakat.
Ketiga, pendidikan budaya disajikan melalui artefak atau bangunan-bangunan dan karya. Ini sudah nyata di depan mata dalam bentuk bangunan, benda-benda seni, dan pagelaran seni budaya.
Dengan ketiga wujud pendidikan budaya tersebut, para santri punya modal penting untuk memahami mana wilayah yang harus diharmoniskan, dikerjasamakan, dikompromikan, diberi toleransi, dan mana wilayah yang dikoreksi, bahkan ada yang harus ditolak.
Kedangkalan seseorang dalam memahami hubungan agama dan budaya kerap menimbulkan problem. Dan ini tidak saja berdampak pada kehidupan individu melainkan dapat mengganggu keharmonisan sosial. Bahkan perlu dijadikan catatan nasional. Saya melihat ada sembilan masalah yang timbul dari kedangkalan tersebut.
Pertama, gagal membedakan unsur agama dan unsur budaya. Misalnya makan nasi kebuli disebutnya mengikuti sunnah Rasul karena Arabnya, tapi makan nasi uduk disebutnya bukan sunnah Rasul karena bukan dari Arab. Ini sebatas joke untuk menjelaskan betapa seringnya kita menjumpai praktik yang timbul akibat gagal paham mana budaya Arab dan mana ajaran Islam.
Misalnya lagi berbuka dengan kurma itu sunnah, tapi berbuka dengan kolak itu bukan sunnah karena buatan Indonesia. Atau lagi misalnya memakai sarung itu tidak islami, tetapi memakai gamis itu islami. Bahkan ada ustadz yang menyebutkan sorban yang dipakai kiai-kiai di Indonesia itu derajatnya sama dengan kain biasa atau sama seperti serbet dan tidak islami karena buatan Nusantara.
Kedua, gagal memahami esensi agama dan tampilan praktik fisik. Tidak semua orang yang menyimpan keris itu musyrik. Karena musyrik dan tidak musyrik bukan soal punya keris atau tidak. Itu soal pilihan kebergantungan hati. Hati yang musyrik menghadirkan tandingan bagi Tuhan.
Orang miskin bisa musyrik dan orang kaya pun bisa musyrik, jika kebergantungan hatinya kepada benda-benda. Demikian juga orang yang tidur di kuburan. Tidak bisa kita menghukumi setiap orang yang tidur di kuburan itu musyrik, jika hatinya bergantung kepada Allah. Bisa jadi mereka tidak punya rumah atau mereka punya maksud tertentu untuk mengingat mati.
Artinya, akidah Islam atau akhlak Islam itu tidak bisa dinilai dari tampilan fisiknya. Justru yang diajarkan Islam adalah esensinya. Bahkan orang yang memberikan uang ke polisi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai suap. Bisa jadi itu paksaan atau sedekah biasa. Tergantung keadaan, alasan, dan tujuannya. Kalau polisi yang memaksa, pasti kedzaliman. Tapi kalau polisinya yang dirayu, namanya penyuapan. Bukankah begitu?
Demikian juga dengan hormat pada bendera atau menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jika dipahami dengan menggunakan teks agama saja, pasti akan dibilang itu bagian dari kemusyrikan. Tapi kalau dipahami sebagai ekspresi budaya bagi orang yang cinta negerinya, ya tidak ada masalah.
Ketiga, beragama dengan dalil yang sempit. Saya kerap mendengar orang bertanya Maulid Nabi itu dalilnya apa, atau setelah shalat bersalaman itu dalilnya apa, atau khaul tahunan itu dalilnya apa, dan lain-lain.
Dalam agama, dalil itu ada dua, yaitu ada dalil naqli (wahyu tertulis) dan dalil aqli. Untuk konteks ibadah muamalah antar manusia, dalil aqli perlu dioptimalkan selama tidak ada larangan dalam dalil naqli.
Maulid Nabi itu pasti bagus secara dalil aqli. Selain tidak ada larangan, pun isinya mengingatkan umat tentang sejarah Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Apa jeleknya? Bahwa konten pendidikannya perlu ditingkatkan lagi, karena yang perlu kita contoh dari Nabi itu bukan semata ibadahnya melainkan perlu mengambil pelajaran dari tata cara hidup beliau, saya juga sepakat itu. Namun, terlalu sempit kalau kita mempersoalkan Maulid Nabi itu dari sisi dalil tekstualnya.
Keempat, mudah memusuhi kelompok lain yang berbeda cara pandangnya. Banyak kelompok yang sekarang ini mudah memberi rapot kepada kelompok lain. Merasa dirinya paling benar lalu menghakimi orang lain dan menyalahkannya kemudian membangun jarak yang merusak persatuan umat.
Padahal yang berbeda hanya di soal-soal furu’iyyah, bukan ushuliyah, seperti PKI. Catatan para kiai menemukan bahwa Kiai Hasyim Asyari itu hanya mengecam Syiah Rafidhah karena mereka mengecam sahabat nabi. Kelompok-kelompok lain yang shalatnya, syariatnya, akidahnya, atau hal-hal usuliah-nya tidak melenceng tetap diterima meskipun ada perbedaan.
Kelima, gagal mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagian masyarakat muslim memang gagal mengikuti perkembangan. Sekadar sebagai tempat sampah teknolobi atau pengguna teknologi semata. Padahal, teknologi itu kalau dioptimalkan sangat bermanfaat.
Saya dan seluruh civitas Bina Insan Mulia merasakan itu. Mengaji disiarkan di Youtube sehingga langsung bisa diakses oleh banyak santri di mana pun berada. Saya menulis apapun di koran, disiarkan secara online. Guru-guru juga saya minta meng-upload semua kegiatan positif di media social.
Demikian juga para santri. Selalu saya minta untuk meng-upload konten-konten positif yang bisa memahamkan dunia luar terhadap pesantren. Bahkan pada bulan Oktober kemarin, saya minta alumni Bina Insan Mulia dari angkatan satu sampai tujuh untuk berkumpul di Luxton Hotel. Selain mendapatkan pembinaan entrepreneurship dan career, saya juga minta mereka untuk aktif mengisi konten positif di medsos.
Kenapa? Saya beberapa kali menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada dunia hari ini adalah perang konten. Semakin banyak informasi positif mengenai pesantren yang dibaca orang luar, maka pemahaman mereka mengenai pesantren semakin bagus.
Keenam, hilang sopan santun karena mengikuti budaya lain. Jika sekolah sudah tidak mengajarkan sopan santun karena mengejar kurikulum, keluarga juga merasa tidak punya waktu dan tidak punya bekal untuk mengajarkannya maka harapannya di pesantren. Jika pesantren juga gagal dalam mengajarkan sopan santun, lalu kepada siapa? Karena itu, di Bina Insan Mulia, sopan santun diajarkan secara kultural. Bahkan tidak sedikit yang bilang bahwa tata krama yang diterapkan di Bina Insan Mulia itu feodal.
Ketujuh, gagal menerjemahkan idiom-idiom agama secara kultural di lapangan. Sejak zaman pesantren ini ada di Indonesia, jihad itu sudah diajarkan dalam kitab fiqih dan kitab-kitab lain. Jihad fii sabilillah itu dibahas panjang lebar, namun tidak ada satupun santri yang berpikir bahwa jihad ini harus diterapkan di Indonesia dalam bentuk mengebom untuk melawan orang kafir.
Kenapa? Karena ada saringan kultural di sana. Para santri menunggu para kiai untuk menerapkan ajaran jihad itu. Demikian juga ajaran mengenai riba, mengenai waris, dan seterusnya. Secara ilmunya sudah ada dari zaman dulu juga, tetapi praktiknya secara kultural membutuhkan kepemimpinan dan keteladanan para kiai, sehingga tidak menimbulkan kegoncangan apa-apa di Indonesia ini. Begitu datang kelompok lain yang tidak mengenal kultur, hanya mengenal teks agama, maka penerapannya menjadi beda.
Kedelapan, kegiatan dakwah malah menjauhkan orang. Dakwah dalam al-Quran adalah mengajak orang ke jalan Allah, bukan mengajak orang mengikuti kelompok kita atau pemikiran kita. Karena mengajaknya ke jalan Allah dengan cara-cara yang bisa diterima oleh hati manusia, maka Wali Songo dulu berhasil meng-Islamkan rakyat jelata sampai raja di Nusantara ini.
Namun, masalah timbul ketika dakwah dipraktikkan dalam bentuk mengajak manusia ke jalan kelompok sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan kultur dan hati manusia. Banyak orang yang sudah Islam malah disalahkan. Ini muncul karena kedangkalan pemahaman pada aspek budaya dan manusia. Dakwah tidak cukup hanya paham teks, lalu miskin pemahaman terhadap konteks.
Kesembilan, salah memilih prioritas dan icon pesan-pesan Islam. Tak bisa dipungkiri bahwa ada bagian dari pesan agama yang menyuruh manusia untuk memberikan respon kekerasan. Salah satunya adalah perang. Namun, kalau dilihat dari keseluruhan ajaran Islam, locus-nya di titik yang sangat terbatas.
Misalnya, perangilah ketika posisimu diperangi. Bukankah itu sangat manusiawi? Engkau diperbolehkan membalas kedzaliman sepadan dengan kedzaliman yang engkau terima. Bukankah ini manusiawai? Namun, agama selalu diberikan pilihan yang lebih tinggi, yaitu memaafkan atau berbuat baik.
Meski ada perintah untuk perang dengan kondisi dan alasan yang sangat manusiawi, tapi kita perlu ingat bahwa prioritas dan icon Islam adalah rahmatan lil alamin, Allah yang Maharahman-rahim, mahabbah, kedamaian, keselamatan, dan peduli terhadap semua makhluk Allah SWT di jagat ini.
Kedangkalan orang terhadap hubungan agama dan budaya akan cenderung mudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non-fisik, baik atas nama agama atau kelompoknya. Mereka mengambil potongan ayat dan hadits Nabi SAW untuk membenarkan tindakannya yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Intinya, dengan pendidikan kultural ini Bina Insan Mulia ingin menghantarkan para santri menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bertauhid, manusia yang berkemanusiaan, dan manusia yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara ini demi mencapai mardhotillah.
Without the BoX Thinking adalah rubrik khusus di tribunnews.com di kanal Tribunner. berisi artikel tentang respon pendidikan Islam, khususnya pesantren terhadap perubahan zaman dan paparan best practices sebagai bahan sharing dan learning di Pesantren Bina Insan Mulia. Seluruh artikel ditulis oleh KH. Imam Jazuli, Lc, MA dan akan segera diterbitkan dalam bentuk buku. Selamat membaca.
*Penulis adalah Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia 1 dan Bina Insan Mulia 2 Cirebon. Pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. Penulis merupakan alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; juga alumnus Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; dan alumnus Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies.*


 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan