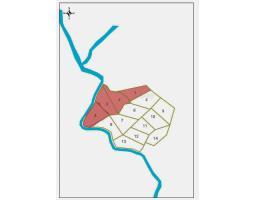Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Catatan Ketua MPR RI: Memampukan Sistem Hukum Ketatanegaraan Kelola Ragam Krisis
Apapun masalah atau krisis yang dihadapi negara, termasuk krisis politik, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan.
Editor: Content Writer
Ditulis oleh:
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA).
TRIBUNNEWS.COM - Negara-bangsa harus mampu mengantisipasi, mengelola dan mengatasi aneka krisis demi tegaknya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya dengan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif dan komprehensif, Indonesia akan dimampukan mengelola dan mengatasi aneka krisis, termasuk krisis politik.
Selain berfungsi merespons, mengelola dan mengatasi ragam krisis, sistem hukum ketatanegaraan yang solutif dan efektif hendaknya juga dipahami sebagai instrumen yang sangat dibutuhkan, bahkan keniscayaan, untuk menjaga dan merawat aspek ketahanan nasional, serta aspek persatuan dan kesatuan negara-bangsa.
Sistem Hukum ketatanegaraan tentu saja harus berlandaskan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Dan, berpijak pada kodrat kebhinekaan bangsa, sistem hukum ketatanegaraan Indonesia hendaknya selalu dijiwai oleh akar budaya serta kearifan lokal yang menjadi sistem nilai semua komunitas anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
Apapun masalah atau krisis yang dihadapi negara-bangsa, termasuk krisis politik sekali pun, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan. Strategi merespons krisis, mengelola dan mengatasi rangkaian masalah yang muncul akibat krisis, hingga kebijakan-kebijakan penyelesaiannya, harus tetap berpijak pada sistem hukum ketatanegaraan.
Setiap individu warga negara tentu saja memiliki hak untuk bereaksi dan bersikap menanggapi dampak atau ekses krisis. Namun, berpijak pada hukum ketatanegaraan itu pula, amuk krisis pada skala sebesar apa pun tidak pernah boleh menoleransi sikap dan tindakan-tindakan inskonstitusional yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional atau mengarah pada upaya merusak persatuan dan kesatuan negara bangsa.
Dalam konteks ini, pernyataan atau catatan yang dikedepankan oleh pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra patut digarisbawahi, untuk kemudian direnungkan oleh segenap elemen bangsa. Patut pula disyukuri karena potensi masalah yang ditunjuk Prof Yusril dikedepankan ke ruang publik ketika negara bersama segenap elemen bangsa sedang melakoni aneka perubahan.
Memang benar bahwa perubahan zaman menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan bernegara-berbangsa, namun perubahan itu nyata-nyata pula telah menghadirkan potensi masalah. Semua potensi masalah itu wajib diwaspadai untuk kemudian disikapi.
Prof Yusril kemudian mengajak semua pihak untuk mengenang kembali krisis politik tahun 1966/67 dan krisis politik tahun 1998. Krisis politik 1966/67 terjadi akibat pergolakan berdarah yang dikenang sebagai peristiwa G-30-S/PKI. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menilai Presiden Sukarno gagal memberi pertanggungjawaban. Pada Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Sukarno, untuk kemudian menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Tahun 1998, faktor ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah dicatat sebagai awal krisis. Kegagalan pemerintah mengatasi krisis ekonomi menimbulkan ketidakpuasan berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa turun ke jalan melancarkan protes atas maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kegagalan pemerintah menanggapi Protes yang meluas saat itu memicu krisis politik.
Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Dasar hukum pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden adalah Tap MPR No. VII/MPR/1973. Tap MPR ini menetapkan bahwa "Jika Presiden berhalangan, maka wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden.”
Pada dua krisis politik itu, MPR masih menggengam amanat penugasannya sesuai UUD 1945 untuk menjalankan kedaulatan rakyat dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah mandataris MPR. Presiden wajib melaksanakan Ketetapan MPR, dan juga diwajibkan memberi laporan pertanggungan jawab mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR.


 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan