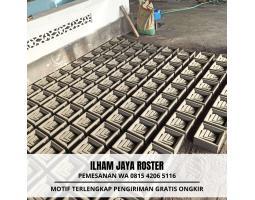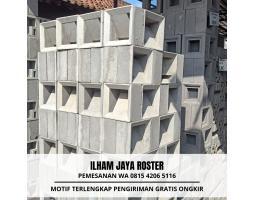Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mendesak Disahkan
Salah satu yang sempat menjadi alasan pembahasan RUU itu mentok adalah perdebatan mengenai hasrat seksual.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini dan muncul dalam perdebatan di media sosial, termasuk kasus fetish menyangkut jarik, memperkuat pentingnya Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertema "Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif" di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Acara itu dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), Diah Pitaloka, yang menjadi pembicara utama di diskusi itu,menyatakan RUU PKS sempat dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
Baca: Kasus Fetish Jarik Viral, Korban Mengaku Jijik dan Berharap Pelaku G Segera Mendapat Hukuman
Salah satu yang sempat menjadi alasan pembahasan RUU itu mentok adalah perdebatan mengenai hasrat seksual.
Dalam perdebatan itu, hasrat seksual didorong tak boleh masuk ke dalam definisi kekerasan seksual.
Namun, kejadian terakhir adalah terjadi praktik fetish kain jarik, dimana terduga pelaku menemukan fantasi seksualnya dengan memanipulasi dan memaksa korban. Maka 'hasrat seksual' dalam definisi kekerasan seksual pun menjadi jelas wujudnya.
"Tadinya dalam pembahasan RUU Kekerasan Seksual, hasrat seksual dipertanyakan dengan sangat keras. Maksud hasrat seksual itu apa? Jadi begitu ada kasus fetish ini, kita bisa menerjemahkan kenapa hasrat seksual masuk dalam definisi kekerasan seksual," kata Diah Pitaloka, Politikus PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR itu.
Karena itulah pihaknya mendorong agar RUU PKS ini kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Masalah lainnya menyangkut konstruksi sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual,
Diah mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan banyak pakar. Dari hasil diskusi terakhir, usulan dari pakar adalah karakteristik hukum yang berlaku adalah hukum pidana khusus.
Dengan begitu, layaknya pidana terhadap korupsi, maka RUU PKS tak perlu menunggu selesainya pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga menjadi alasan lain kenapa RUU PKS sempat dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.
"Itu menjawab pertanyaan apakah Undang-Undang PKS ini harus menunggu KUHP atau tidak. Ternyata undang-undang ini mengandung kekhususan hukum," imbuhnya.
Diah lalu mengingatkan, salah satu substansi alasan pentingnya RUU ini adalah karena berdasarkan pengakuan korban, banyak kasus kekerasan seksual berbasis relasi pelaku dan korban yang tidak setara. Sehingga ada dominasi, tekanan, manipulasi.
"Semoga RUU ini menjadi RUU yang diketengahkan sebagai bentuk political will, goodwill, keinginan baik yang diterjemahkan ke dalam ruang politik oleh fraksi-fraksi di DPR RI," katanya.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar, menyampaikan bahwa lembaga itu kerap terhalang bila hendak melindungi korban kekerasan seksual yang mengadu karena ketiadaan dasar hukum.
Ada berbagai kasus dimana korban melapor karena berada di bawah ancaman pelaku kekerasan seksual. Sejauh ini, yang bisa dilaksanakan pihaknya adalah mencoba berkoordinasi dengan para psikolog untuk membantu para korban.
Pihaknya mencatat sejumlah poin yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU PKS. Pertama adalah soal pemenuhan hak prosedural, hak psikologis, dan restitusi.
Kedua, kasus di Bengkulu dimana keluarga korban justru dikucilkan oleh masyarakat. Ini berarti perlu mengatur kerangka sosio-ekologis dimana masyarakat tidak boleh menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan seksual.
Selanjutnya adalah kasus kekerasan seksual dalam hubungan inses dimana keberulangan sangat tinggi terjadi.
"Penegak hukum juga harus responsif korban. Maksudnya paham hak-hak saksi dan korban, sehingga nanti penanganan perkara menjadi suatu kebutuhan.
Penuntut umum dan hakim itu paham tentang apa yang harus dilalui korban. Ini dipaksa ngomong berkali kali, saya membayangkan harus berapa kali si korban ini menyampaikan apa yang terjadi pada dia. Itu menyedihkan," bebernya.
Soal pembuktian hukumnya juga harus diatur jelas. Bagi Livia, keterangan seorang saksi korban saja semestinya sudah cukup untuk membuktikan dugaan kekerasan seksual.
"Victim impact statement, RUU PKS harus mengadopsi konsep partisipasi korban dalam proses peradilan pidana. Dimana si korban dapat memberikan pernyataan kejahatan yang menimpanya, baik berupa tulisan maupun lisan.
Pernyataan itu ditujukan kepada hakim dan dibacakan. Ini supaya bisa mendengar langsung bagaimana peristiwa tersebut mengubah hidup seorang korban," tambah Livia.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan