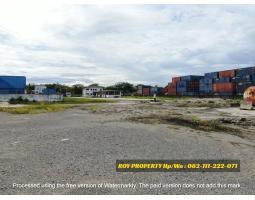Ancaman Kedaulatan Datang dari Laut China Selatan, Jakarta Harus Bersiap Menghadapi Risiko Terburuk
Merespons potensi konflik Laut China Selatan, opsi menghadapi risiko terburuk harus tetap ada dalam kalkulasi Pemerintah Indonesia.
Penulis: Malvyandie Haryadi

Dari rentetan contoh kasus di atas, muncul sejumlah pertanyaan, apa yang harus dilakukan Indonesia merespons pelanggaran dan ancaman kedaulatan di Laut China Selatan?
Dalam jangka pendek, Jakarta mungkin bisa lebih banyak mengerahkan kapal-kapal Coast Guard ke wilayah tersebut, seperti yang disarankan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Irvansyah.
Ia beralasan, sejauh ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik di Laut China Selatan maupun di Laut Natuna Utara banyak dilakukan kapal-kapal sipil.
"Kami berpandangan jika yang dimajukan adalah kapal-kapal militer milik TNI AL, justru berpotensi meningkatkan tensi ketegangan. Sebab kebanyakan pelanggar di sana adalah kapal sipil, baik kapal nelayan maupun kapal Coast Guard milik China," kata Irvansyah dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Namun, patut diingat, persoalan di Laut China Selatan cukup kompleks, melibatkan sejumlah negara, dan disebut berpotensi mengarah ke konflik terbuka. Apa yang harus dipersiapkan Jakarta? Perlukah Indonesia meninggalkan sikap "nonblok", kebijakan bebas-aktif, dan merapat ke salah satu kubu, entah AS atau China?
Profesor Edwin Martua Bangun Tambunan, Guru Besar Bidang Keamanan dan Perdamaian di Universitas Pelita Harapan berpendapat, apa yang dilakukan Indonesia dalam kasus Laut China Selatan bukanlah "menampilkan" orientasi non-blok, melainkan menunjukkan independensinya.
Menurut Edwin, lewat kebijakan independensinya, Indonesia bebas untuk menentukan sikap dan tindakannya sejauh itu bermanfaat untuk pencapaian kepentingan nasional.
"Posisi ini apabila diterapkan dengan efektif akan semakin membuat posisi tawar Indonesia menguat dan menjadi lebih diperhitungkan. Hanya saja, posisi ini akan rawan terhadap tekanan apabila Indonesia tidak memiliki kemandirian untuk membangun kapabilitas militernya dalam jangka panjang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa (28/5/2024).
Lebih jauh, Prof Edwin mengatakan, dalam kajian politik internasional apa yang dilakukan oleh Indonesia ini adalah penerapan strategi hedghing, yaitu membangun relasi yang terukur dengan dua kekuatan besar sehingga membuka peluang terjadinya keseimbangan kekuasaan.

Dalam hal ini, menurutnya, peran intermediary yang dimainkan Indonesia menjadi penyeimbang atas kontestasi China dan AS di Asia Tenggara sekaligus menjadi katup pengaman untuk mencegah kontestasi berubah menjadi konflik terbuka.
Meski, Edwin meyakini, sejauh ini, China masih sangat berhitung dan tidak akan memaksakan kekuatan militernya untuk terjebak dalam perang besar dengan siapapun, termasuk kekuatan luar kawasan seperti AS.
"Ada peluang yang dibaca China, yaitu tujuannya untuk memenangkan klaim atas LCS masih dapat dicapai dengan memanfaatkan instrumen ekonomi dan pengaruh politik untuk melemahkan resistensi negara-negara claimants dari dalam, sekaligus melemahkan ketergantungan mereka terhadap kekuatan besar dari luar kawasan," ujarnya.
Pun demikian dengan Amerika Serikat di sisi lain. Dalam pandangan Edwin, AS tidak akan siap untuk perang besar karena dalam penilaian objektif Washington, kapabilitas yang dimilikinya saat ini belum mumpuni untuk memenangkan pertempuran. "Oleh karena itu, AS akan berupaya menghindarkan terjadinya perang terbuka."
Namun, terlepas dari pilihan kebijakan Washington atau Beijing terkait konflik Laut China Selatan, opsi menghadapi risiko terburuk tetap harus ada dalam kalkulasi Jakarta.
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan