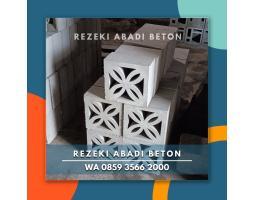Pengamat Energi: Kebijakan Uji Emisi Saja Tidak Akan Cukup Atasi Kualitas Udara
Sektor transportasi berkontribusi sebesar 44 persen atas penggunaan bahan bakar di Jakarta.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Energi Muhammad Badaruddin mengatakan pemerintah seharusnya menyoroti aspek kualitas bahan bakar minyak (BBM) kendaraan karena kontributor emisi terbesar saat ini adalah sektor transportasi.
Data valid dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, sektor transportasi berkontribusi sebesar 44 persen atas penggunaan bahan bakar di Jakarta.
Itu terdiri dari 17 juta sepeda motor, 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk, dan 344 ribu bus.
Diikuti industri energi 31 persen, lalu manufaktur industri 10 persen, sektor perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.
"Ini menjadi bukti bahwa kebijakan uji emisi saja tidak akan menjadi solusi. Sebab, masalahnya bukan hanya pada persoalan mesin kendaraan yang kotor, namun juga disebabkan kualitas BBM yang tidak memenuhi standar Euro 4 yang telah ditetapkan oleh pemerintah," tutur pria yang karib disapa Badar ini di Jakarta, Sabtu (16/3/2024).
BBM jenis bensin yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah Pertalite dan Pertamax.
Badar bilang dua jenis bensin tersebut belum memenuhi standar bahan bakar untuk jenis mesin Euro 4, yang mampu mengeluarkan emisi yang lebih bersih dibandingkan dengan BBM lainnya.
Padahal, KLHK telah mengatur BBM harus berstandar emisi Euro 4, yang berlaku bagi kendaraan roda empat berbahan bakar bensin sejak Oktober 2020.
Baca juga: Banyak Tuai Protes, Polisi Kembali Tiadakan Tilang Uji Emisi untuk Kendaraan di Jakarta
Industri otomotif dalam negeri juga sudah memproduksi mobil yang memenuhi standar Euro 4.
"Namun ironisnya, bagian besar bahan bakar yang digunakan di Indonesia, baik itu bensin maupun solar masih belum memenuhi standar emisi Euro 4. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling tertinggal di Asia Tenggara, dalam komitmen peralihan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," ujar Badar.
Badar mengungkapkan, berdasarkan data KPBB, saat ini Indonesia menjadi negara terakhir di Asia Tenggara yang belum mengadopsi standar Euro 4. Negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia sudah mengadopsinya.
Baca juga: Hasil Survei Populix: Mayoritas Warga Jabodetabek Siap Terapkan Uji Emisi
Bahkan Singapura sudah mengadopsi standar Euro 6.
BBM standar Euro 4 ini kerap dikatakan jika kandungan sulfur dalam bahan bakar tidak melebihi 50 parts per million (ppm).
Namun perlu diketahui bahwa Euro 4 bukan sekedar sulfur saja tetapi meliputi pembatasan kadar kandungan senyawa kimia berbahaya seperti benzena, aromatik, olefin yang menyebabkan pencemaran udara dan merusak sistem pernapasan.
BBM berstandar Euro 4 juga memiliki batas kandungan benzena maksimal 1 persen (v/v), aromatik maksimal 35 persen (v/v) dan olefin maksimal 18 persen (v/v).
Sementara, spesifikasi BBM Pertamax maupun Pertamax Green 95 memiliki batas benzena maksimal 5 persen (v/v), aromatik maksimal 40 persen (v/v) dan olefin 20 persen (v/v).
Sedangkan, BBM Pertalite tidak memiliki batas maksimal kandungan senyawa kimia tersebut, namun cukup dilaporkan.
Terkait dengan penggunaan bioetanol sebagai bentuk transisi energi bersih sebagaimana yang digaungkan saat ini tak menjamin bisa mengatasi kualitas udara yang semakin memburuk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bioetanol bisa meningkat senyawa organik mudah menguap atau volatile organic compounds karna tekanan uap bensin lebih tinggi.
Oleh karena itu, Mexico telah melarang penggunaan bioetanol di kota besar seperti Mexico City, Guadalara dan Monterrey.
"Namun demikian, alih-alih meningkatkan kualitas BBM sesuai standar Euro 4 yang urgen dilakukan saat ini untuk meningkat kualitas udara yang bersih, justru ada upaya untuk mendorong bioetanol yang membutuhkan investasi besar dari hulu hingga hilir dan waktu yang panjang. Padahal, kesehatan dan hak masyarakat, adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi," sesal Badar.
Badar melihat, implementasi bioetanol juga menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau ngotot akan menggunakan bioetanol, maka ketergantungan kita pada impor akan meroket, karena pasokan bioetanol domestik saat ini tidak cukup. Sehingga mau tidak mau justru akan membuka keran impor bioetanol dan ini berdampak kepada petani dan produsen lokal dan membuat harga BBM semakin tidak terjangkau," tukas Badar.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan Indonesia butuh waktu untuk memanfaatkan bioetanol secara besar-besaran.
Bahan baku masih menjadi tantangan untuk pengembangan bioetanol ini.
Menurut Tutuka, pengembangan bioetanol tidak bisa secepat biodiesel. Sementara, jika menggunakan bioetanol impor akan berdampak pada biaya dan harga bahan bakar.
"Itu masih agak lama etanolnya karena pakai apa kita. Kalau biodiesel kita punya hulunya, kelapa sawit, tapi ini kan kita belum punya. Awal rantai pasoknya nggak punya di hulunya, jadi menurut saya tidak bisa cepat seperti biodiesel. Karena kalau impor pasti akan tambah biaya dan tinggi harganya," terangnya.
Argumentasi yang dikemukakan Tutuka Ariadji tersebut semakin memperjelas pendapat Badar bahwa penggunaan bioetanol untuk kendaraan bermotor perlu dievaluasi.
Terutama karena bioetanol dipromosikan sebagai solusi hijau, “green”, namun jika melihat spesifikasi Pertamax Green 95 dan batas maksimal kandungan sulfur dan senyawa kimia, tidak ada perbedaan signifikan dengan spesifikasi Pertamax saat ini.
Demikian, Pertamax Green 95 pun belum bisa dikatakan memenuhi standar Euro 4 walaupun oktanya lebih tinggi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan