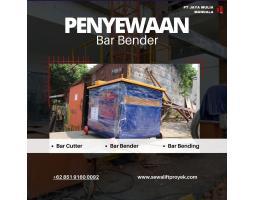Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Rahasia di Balik Pesantren Berwajah Etnik, Yang Wajib Anda Ketahui
Tidak jarang karya arsitektur tersebut dihasilkan dari upaya-upaya serius untuk menggabungkan aspek Islam.
Editor: Husein Sanusi
Jujur saja, pesantren termasuk lembaga terdepan dan yang paling peduli untuk urusan pelestarian budaya. Cuma memang jarang pemerintah atau sebagian masyarakat melihatnya dari aspek itu. Malah pesantren pernah dicap dengan stempel yang tidak-tidak. Sarang teroris lah, radikal lah, atau anti NKRI lah.
Apa bukti pesantren itu sangat peduli pada budaya? Sejak ratusan tahun lalu, pesantren telah menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tingkat tinggi untuk menerjemahkan kitab yang berbahasa Arab.
Dan sampai saat ini, pesantren yang tetap menggunakannya tetap ada meskipun jumlahnya terus berkurang. Kenapa kok berkurang? Ini bukan tugas pesantren, tetapi tugas kementerian pendidikan: kenapa semakin banyak bahasa daerah yang tergerus oleh perubahan zaman. Padahal bahasa menjadi salah satu modal sosial dan menunjukkan eksistensi bangsa.
Bahkan bahasa sehari-hari yang digunakan di pesantren untuk menjelaskan hubungan antara guru, santri, dan kiai itu bahasa Jawa yang tinggi. Bagaimana di tempat lain? Misalnya di Banten, di Cirebon, di Sumatera, di Kalimantan, di NTB, atau di Aceh? Sama juga. Masyarakat pesantren memilih tingkat bahasa yang tinggi untuk berkomunikasi.
Percakapan antara KH. Hasyim Asy a’ri dan KH. Wahid Hasyim tetap menggunakan bahasa Jawa yang tinggi meskipun beliau berdua lama di Mekkah. Bahkan Kiai Marzuqi Lirboyo tidak menggunakan bahasa Jawa kelas awam untuk berbicara dengan santrinya. Beliau menggunakan bahasa Jawa kromo alus dengan para santrinya untuk menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan soal bahasa verbal semata, tetapi mengandung tata krama.
Itulah yang dicontoh para kiai dalam melestarikan budaya. Selain bahasa dan tata krama, pesantren juga melestarikan produk budaya lain, yaitu pakaian. Saya kemana-mana menggunakan sarung, kemeja, kopyah dan sandal. Lucunya, ketika saya masuk beberapa kota, justru saya yang dibilang ganjil secara budaya, padahal inilah budaya asli kita.
Kopyah dan sarung itu sejatinya tidak identik Islam tapi Nusantara. Lihat, di zaman Pak Harto dulu, semua pejabat pakai kopyah keman-mana, apalagi pada acara-acara resmi. Demikian juga sarung. Bagi orang Aceh, Jawa Barat, Betawi atau di beberapa tempat lain, sarung itu bukan untuk shalat saja. Pagelaran budaya yang mereka atraksikan di panggung juga menggunakan sarung.
Contoh-contoh sekilas di atas hanyalah sebagian kecil dari perhatian pesantren terhadap pendidikan budaya. Apa sejatinya pendidikan budaya di pesantren, khususnya di Bina Insan Mulia?
Sebagaimana sudah diketahui umum, budaya adalah tata cara hidup yang diciptakan manusia dalam sebuah masyarakat dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu. Dalam perjalanannya, budaya itulah yang menjadi karakteristik atau ciri khas utama masyarakat tersebut.
Budaya Bali berbeda dengan budaya Sunda dalam beberapa hal. Budaya Arab berbeda dengan budaya Nusantara dalam beberapa hal. Budaya Barat berbeda juga dengan kita. Masyarakat membangun budaya dari generasi ke generasi lalu menjadi kode sosial. Budaya kemudian menjadi identitas, bahkan menjadi kekayaan suatu masyarakat.
Tata cara hidup yang disebut budaya itu kemudian oleh sebagian ahli dijabarkan ke dalam unsur-unsur budaya. Secara umum, unsur budaya mencakup antara lain: a) sistem dan adat istiadat keagamaan, b) sistem dan organisasi kemasyarakatan, c) sistem pengetahuan, d) bahasa, e) kesenian, f) sistem mata pencaharian hidup, dan g) sistem teknologi dan peralatan.
Apa hubungannya dengan pesantren? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam. Sudah pasti keislaman menjadi karakteristik utama. Lalu kenapa harus ada budaya?
Hubungan antara Islam dan budaya memang sangat luas, multi dimensi, dan tidak bisa dijelaskan secara hitam-putih, haram-halal. Namun, untuk konteks pendidikan budaya di Pesantren Bina Insan Mulia, saya hanya ingin menjelaskan beberapa poin saja untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman budaya sebagai dukungan terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan keislaman dalam masyarakat.
Budaya adalah produk dari manusia, sedangkan agama adalah produk dari Allah SWT atau wahyu. Apakah keduanya harus dipertentangan atau dipertemukan atau dikerjasamakan? Jawabannya jelas tergantung.
Untuk budaya yang positif atau budaya yang baik, budaya tersebut harus diikutkan sekalipun untuk pelaksanaan ibadah yang formal (mahdhoh). Shalat itu yang isinya dari agama terdapat pada gerakan, ucapan, dan aktivitas hati lalu tanah untuk bersujud dan penutup aurat secukupnya. Sisanya dimainkan oleh faktor-faktor budaya. Misalnya sarung, pakaian, masjid, tempat wudhu, kopyah, serban, atau pengeras suara.
Demikian juga puasa. Yang heboh di Indonesia itu bukan unsur agama dalam puasa Ramadhan, tapi lebarannya atau menunya atau hubungan antara momen puasa Ramadhan dan dampak ekonominya. Demikian juga haji. Aspek ajaran agamanya sedikit sekali. Sisanya adalah kebutuhan yang muncul dari budaya, mulai paspor, tes kesehatan, hotel, makan, pakaian, dan lain-lain.
Bahwa seringkali konsentrasi pada pemenuhan kebutuhan budaya lebih menyita perhatian umat beragama ketimbang tuntutan ajaran, memang ini perlu dikoreksi bersama. Jangan sampai esensi ibadah formal itu hilang di tengah hiruk pikuk perayaan budaya.


 Baca tanpa iklan
Baca tanpa iklan